Budaya Tanding dan Resistensi Pendidikan Alternatif
Setarikan napas dengan opini Aprinus Salam di KR (Jumat, 8 Juni 2018) berjudul Membongkar Resistensi, hegemoni, sebagai kata benda dan memiliki spirit epistemologis, sesungguhnya menjalar ke tiap lini kehidupan. Termasuk dominasi kebudayaan partikular, sebagaimana ditesiskan Aprinus karena ia masuk ke dalam “wilayah kontestasi”. Gambaran besar mengenai kebudayaan itu antara lain juga mengerucut ke ranah pendidikan.
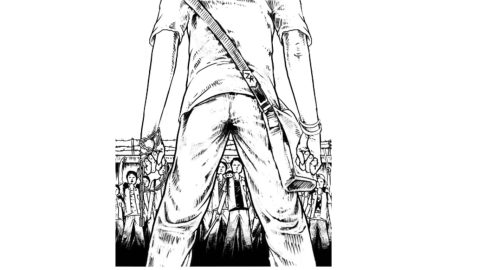
Suminto A. Sayuti pernah mengatakan kedudukan pendidikan sebagai alat pembudayaan bangsa. Orientasi aksiologis pembudayaan itu diarahkan guna “pemberadaban manusia” yang praksis di lapangan acap diinterpretasikan pemerintah menjadi pendidikan karakter. Problem karakter inilah seakan-akan hulu dari kerusakan moral bangsa sehingga diperlukan rumusan praksis seperti kurikulum pendidikan karakter. Di satu sisi ia juga menginduk pada spirit revolusi mental yang dinarasikan Presiden Jokowi.
Kedudukan pendidikan karakter yang dirumuskan pemerintah adalah manifestasi formal dari praktik hegemoni dalam jagat pendidikan nasional. Realitas demikian lazim terjadi pada tiap diskursus yang digencarkan pemerintah terpilih. Cakupan pendidikan karakter di sini dapat ditelisik lebih mendasar sebagai acuan atas perilaku amoral yang dilakukan seseorang.
Dalam potret banalitas remaja, aksi klitih yang baru-baru ini mengemuka dan menimbulkan kecemasan sosial, pendidikan karakter (moral) ditengarai mampu mereduksi perilaku tersebut secara cespleng. Keputusan untuk mendasarkan pendidikan moral dalam rangka mereduksi banalitas remaja di satu sisi baik, namun di sisi lain menjadi hal problematik karena tak mengindahkan faktor determinan lain secara mendalam: sosio-kultural, ekonomi, dan lain sebagainya.
Mendasarkan preferensi moral sebagai bagian dari orientasi pendidikan nasional mutakhir adalah sepenuhnya hak otoritatif pemerintah. Kuasa atas kebijakan pendidikan semacam itu, dengan kata lain, merupakan wujud eksplisit dari praktik hegemoni. Dengan demikian, institusi pendidikan formal menempati posisi strategis dalam melanggengkan visi hegemonik itu.
Budaya Tanding
Tembok besar bernama politik pendidikan sebagai wajah kekuasaan menarik ke medan resistensi. Hal ini lazim terjadi karena seperti pernyataan Aprinus “tidak ada dominasi atau hegemoni yang sempurna” sehingga meniscayakan pergulatan ideologi di antara pihak oposisi. Tesis dan antitesis dimungkinkan atas dasar pusparagam perspektif yang bukan sekadar disulut oleh sudut pandang, melainkan juga jarak pandang dan resolusi pandang (Panuluh, 2017).
Dalam konteks kebijakan pendidikan, kritik demi kritik dialamatkan oposisi ke pihak pemegang kekuasaan, namun kenyataannya justru dipandang negatif karena dianggap menyerang personal. Penembak dan penerima kritik acap kali gagal paham oleh karena dua hal. Pertama, substansi kritik dicorongkan dalam rangka membenahi keganjilan kebijakan pendidikan tapi direspons ahistoris—lebih diterima sebagai bagian dari “meruntuhkan” dominasi individu.
Kedua, budaya kritik belum mengakar kuat di kalangan masyarakat. Realitas di lapangan, karenanya, justru dijungkirbalikkan, bahkan ontologi kritik direduksi serampangan, sebagai bagian buruk dari percakapan sosial yang semestinya dihindari. Penyebabnya bisa beragam, yakni kecenderungan asal bapak senang (ABS) dan budaya pakewuh masih mengakik di kalangan lintas hierarki masyarakat.
Bila ditelisik lebih lanjut, budaya tanding dalam rangka kontestasi ideologi yang menghasilkan tesis dan antitesis sebetulnya berperan signifikan untuk membentuk demokratisasi pemikiran. Sumbangsih pemikiran, dengan koridor saling membuka diri dan menghormati liyan, adalah ekspresi kultural nilai bebrayan agung. Nilai ini sedemikian luhur di masa silam tapi kerap kali dilupakan generasi milenial, bahkan dimaknai sebatas pertemuan fisik. Padahal, ia melampaui segi fisik karena menyiratkan nilai-nilai imateriel.
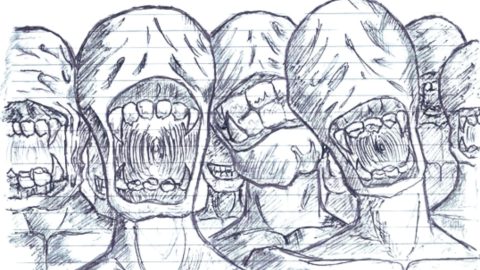
Dikotomi Pendidikan
Hegemoni kebijakan pendidikan setidaknya dapat dibagi menjadi dua arus secara fisik dan nonfisik. Cakupan nonfisik meliputi pendidikan karakter sampai aras kebijakan-kebijakan (kurikulum) struktural lain. Sedangkan dimensi fisik, seperti diketahui jamak orang, resistensi pendidikan alternatif versus pendidikan formal (sekolah). Di sisi pemegang kebijakan sekolah formal, pendidikan alternatif dipandang sebelah mata karena dianggap keluar aturan.
Berbeda dengan pendidikan formal, pendidikan alternatif tak menginduk sepenuhnya di bawah struktur pemerintah pusat. Posisi ini tegas dilakukan, semisalnya, melalui aspek kurikulum hingga metode pembelajaran. Pendidikan alternatif mengonstruksi model belajar khusus dalam rangka berdaulat atau terlepas dari cengkeraman hegemoni pendidikan formal. Di Indonesia jumlahnya relatif banyak, baik di tingkat daerah maupun provinsi.
Pendidikan alternatif melakukan resistensi karena hendak menyuarakan otonomi partikular yang menawarkan konsep pedagogik baru. Di tengah praktik pendidikan yang serba formalistik, pendidikan alternatif melakukan suatu dorongan pembebasan. Upaya tersebut di satu sisi direspons positif, namun di sisi lain juga menuai komentar negatif. Terlepas dari oposisi biner di sana, bila diteroka secara universal, keduanya justru saling memperkaya dan melengkapi.
Pemerintah sudah semestinya melihat realitas antara pendidikan formal dan pendidikan alternatif secara obyektif. Kontribusi keduanya tak diragukan dalam jagat pendidikan nasional. Keduanya senada, meski berbeda ideologi, dalam menafsirkan ikhtiar “mencerdaskan kehidupan bangsa”. [] bersambung
Peneliti Pendidikan, Penulis Buku Genealogi Hoaks Indonesia



Leave a Reply