Mulai hari ini akan diturunkan secara bersambung seri tulisan Sketsa Politis Pendidikan Kritis oleh Rony K Pratama (Penulis ”Manusia Tanpa Sekolah”) diterbitkan oleh Bentang Pustaka.

Hari Anak dan Literasi Berbasis Laku
Pada medio bulan Juli jamak orang memperingati Hari Anak Nasional. Seremoni kemudian digeliatkan di pelbagai ranah berikut pusparagam tipe perayaannya. Anak dipandang penting diwacanakan sebagai sebuah acara monumental. Nasibnya digadang-gadang dan dilejitkan potensi personalnya dalam rangka mempersiapkan bonus demografi yang konon akan dinikmati sekian dekade mendatang. Anak, dengan kata lain, menjadi kata kunci yang acap dicari, namun pada gilirannya juga sering diabaikan hanya sebatas kelas subordinatif.
Banyak orang merasa cemas karena rangking literasi bangsa Indonesia rendah ketimbang negara-negara lain di dunia. Programme for International Students Assessment (PISA) merupakan salah satu lembaga survei internasional yang menyodorkan peringkat literasi dunia.
Hasil termutakhir, pada 2016, PISA menyampaikan ketercapaian literasi dan menempatkan Indonesia di urutan 64 dari 70 negara. Hasil itu membuat ketar-ketir publik, terutama pemerintah Indonesia. Sebagian masyarakat kembali menanyakan ulang: benarkah kecakapan literasi bangsa Indonesia rendah?
Publik luput menginterpretasikan rendahnya literasi bangsa Indonesia. Selama ini mereka menggeneralisasikan hasil PISA sebagai potret universal keterpurukan literasi di negeri khatulistiwa. Padahal, subyek utama penilaian PISA adalah siswa-siswi berusia 15 tahun yang metode penentuan sekolahnya dipilih secara acak. Yang menjadi persoalan berikutnya, apakah wajah pelajar berusia remaja itu merupakan representasi bangsa Indonesia?
Penyamarataan kompetensi literasi, sebagaimana kerap dikeluhkesahkan khalayak, adalah suatu bentuk ketidakbijaksanaan akademis. Terlepas dari limitasi PISA sebagai institusi penilai literasi, di satu sisi niscaya terikat pada segi konteks dan metode, sedangkan di sisi lain tak boleh diremehkan. Ihwal rendahnya literasi tentu harus dijadikan refleksi untuk perbaikan konstruktif, terutama menyangkut pendidikan literasi yang selama ini bagai hidup segan mati tak mau.
Pustaka Bergerak adalah contoh konkret bagaimana literasi dimasyarakatkan melalui program distribusi buku ke pelosok tanah air. Komunitas-komunitas literasi di belahan daerah juga turut memperkaya diskursus pendidikan literasi. Gerakan Literasi Sekolah (GLS) sebagai program pemerintah ikut pula membangkitkan spirit pustaka di ranah pendidikan formal. Pendeknya, semua elemen itu mesti dicatat dan diselebrasikan dalam rangka antitesis terhadap anjloknya kemampuan literasi bangsa Indonesia.
Apakah pelbagai pihak yang bergerilya di wilayah literasi itu mampu menaikkan rangking literasi versi PISA itu persoalan lain yang harus ditelisik secara saintifik. Lebih penting ketimbang meratapi nasib soal buruknya kemampuan literasi, gerakan sosial yang bersifat kultural, sistematis, dan masif—baik bergerak secara formal maupun nonformal—harus terus dihela karena betapapun ia menyiratkan investasi (intelektual) masa depan.

Komponen Fundamental
Anak menempati posisi strategis sebagai obyek aktif yang secara psikologis mampu menerima, mengolah, dan memproduksi kecakapan literasi. Daripada orang tua yang relatif sukar mempelajari sesuatu yang baru, anak justru sebaliknya: masih segar dibentuk serta membentukkan diri secara kreatif dan mandiri. Pada aras demikian, habituasi pendidikan literasi dinilai tepat diajarkan untuk usia anak.
Pelajaran krusial pendidikan literasi untuk anak mesti dimulai dari pola didaktik berbasis kebiasaan. Sedangkan kebiasaan, pada gilirannya, ditempakan melalui strategi aksi-reaksi, yakni memposisikan literasi bukan sekadar teori, melainkan sebuah laku. Posisi ini mengacu pada ajaran klasik berupa macapat di serat Wulang Reh karangan Sri Susuhunan Pakubuwana IV (1768-1788) yang menegaskan ngelmu iku kalokane kanthi laku.
Tafsir mengenai laku bisa beraneka rupa tergantung metode, strategi, dan acuan referensialnya. Namun, mengkontekstualisasikan laku di era disrupsi jelas mustahil terlepas dari teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai media canggih ia membuka peluang bagi segenap potensi sibernya untuk diakses dan digumuli. Anak, karenanya, hendaknya diperhadapkan dengan media internet melalui bimbingan terpadu.
Anak dan internet merupakan dua anasir yang kini tak terpisahkan. Agar pendidikan literasi tak ahistoris, orang tua sebagai pemandu harus cerdas membimbing karena selain sisi positif, internet juga sumber negatif. Takaran pendidikan literasi berbasis media semestinya dijalankan penuh tanggung jawab. Nilai ini kian sirna di tengah kondisi orang tua yang sepenuhnya menyerahkan nasib anak kepada institusi pendidikan formal semata. Orang tua, betapapun, menjadi kunci mayor pendidikan literasi bagi anak.
Hari Buku, Antara Membeo dan Tradisi
Pekan terakhir bulan April jamak orang memperingati hati buku sedunia. Limimasa media sosial penuh dengan curahan sepintas mengenai buku. Penuh dengan glorifikasi sesaat, peringatan warganet terhadap buku bertahan temporal. Buku di satu sisi ditagarkan berbondong-bondong, sedangkan kehadirannya di sisi lain sebatas ucapan verbal. Eksis dalam simbol tagar dan narasi status, buku kemudian ditenggelamkan lekas.
Merayakan hari buku berarti menandaskan arti kebebasan pengetahuan. Tiap orang berhak merayakannya meski disampaikan sepintas lalu. Momen tahunan ini pun sekadar disakralkan ke dalam satu hari. Selebihnya buku, betapapun genrenya, ditinggalkan. Minimal dipajang sebagai amsal intelektual seseorang.
Bagaimana seharusnya merayakan hari buku? Apakah ada upacara khusus yang mesti dilakukan? Dua pertanyaan ini mirip prosedur protokoler yang serba formal, baku, dan penuh khidmat. Sayangnya buku bukan barang milik para cendekiawan menara gading. Walaupun kedudukannya dikuduskan karena memuat bejibun informasi, merayakan buku bisa dilakukan dengan beragam cara.
Tata cara merayakan buku itu gampang. Semudah membubuhkan status media sosial. Yang sukar dari peringatan buku adalah konsistensi untuk tekun membaca. Keterampilan membaca ini, dengan demikian, adalah kunci utama memestakan buku. Oleh karena mendaras sebagai kata kunci meramaikan buku, ia harus dilakukan dalam rangka habituasi.
Mengkultuskan hari buku sedunia tanpa mentradisikan mendaras buku ke dalam laku sehari-hari serupa mengkhianati momen suci. Tekad bulat untuk membawa spirit hari buku tak terbatas pada hari tertentu adalah konsekuensi logis lain yang mesti diwacanakan. Ini PR terbesar umat manusia, terutama warganet, yang sudah terlanjur membeo dalam peringatan hari buku sedunia di jagat siber.

Habituasi dan Konsistensi
Rumus mudah menggumuli buku adalah iktikad kuat untuk membacanya sampai tuntas. Dengan begitu buku bukan sebatas perabot sekunder rumah tangga, melainkan memuat kandungan nilai-nilai intrinsik. Laku semacam ini tanpa sadar mengubah kedudukan buku dari yang acap dikatakan benda mati menjadi difungsikan sebagai benda hidup.
Kehidupan buku mulanya hadir di benak penulis. Berkat abstraksi konseptual yang diejawantahkan secara tertulis, buku mulai kehidupan baru usai ditangani penerbit berikut distributornya. Roland Barthes mengemukakan pengarang telah mati usai ia menyelesaikan karangannya. Agar hasil karya itu tetap hidup ia mesti dibangkitkan melalui proses mendaras. Semakin buku itu dibaca, semakin hidup ia di benak orang.
Pekerjaan pembaca untuk menghidupkan buku ke dalam pengalaman kemanusiaanya itu secara sederhana bisa ditempuh dua cara. Pertama, membaca literal dengan usaha sadar yang dilakukan pembaca untuk menyerap tuntas isi buku. Membaca seperti ini lazim diposisikan pada level membaca dasar. Pembaca hanya meresap informasi yang tertulis tanpa teding aling-aling.
Kedua, membaca kritis yang meniscayakan dialektika antara pembaca dan penulis melalui isi buku. Model membaca demikian masuk ke dalam kategori tinggi karena membutuhkan keterampilan ekstra untuk tak sekadar menyerap informasi, tetapi juga mengkritisi bacaan. Pembaca yang berada pada level mengkritisi apa yang dibaca tentu telah memiliki bangunan pengetahuan yang nyaris sama atau mendekati bacaan tertentu.
Mendaras secara kritis memungkinkan pembaca meneroka makna di balik teks. Ia seakan-akan bisa meneropong alasan psikologis, sosiologis, dan pragmatis kenapa penulis membangun argumentasinya seperti yang ia konstruksi di bukunya. Lapisan paling elementer untuk membaca kritis antara lain jeli terhadap diksi, susunan sintaksis (kalimat), hingga bangunan ide yang membentuk wacana utuh.
Di mana posisi pembaca dewasa ini bila merujuk pada kategorisasi di atas akan mengantarkan pada sketsa tradisi membaca jamak orang. Menganalisis kecenderungan tersebut membutuhkan penelitian panjang dan memakan banyak duit. Namun, setidaknya ia bisa dijadikan pedoman diri untuk merefleksikan sejauh mana progres keterampilan membaca masing-masing orang. [] bersambung …
Peneliti Pendidikan, Penulis Buku Genealogi Hoaks Indonesia
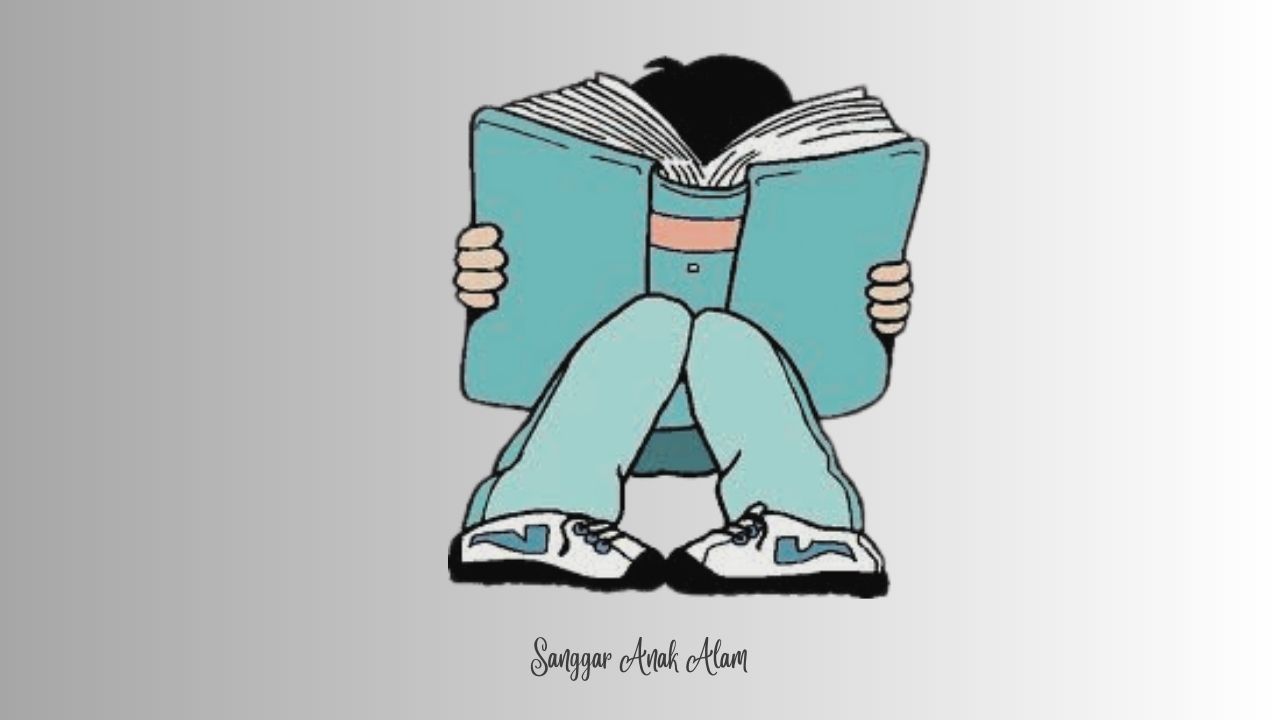


Leave a Reply