Pengertian pendidikan dan belajar sudah diambil alih cukup lama dan panjang oleh jagad sekolah, hampir sebagian besar masyarakat menganggap bahwa pendidikan adalah sekolah. Jadi, jika orang tidak sekolah maka orang tersebut dianggap tidak berpendidikan—demikian juga jika oran tidak sekolah maka dianggap tidak belajar.
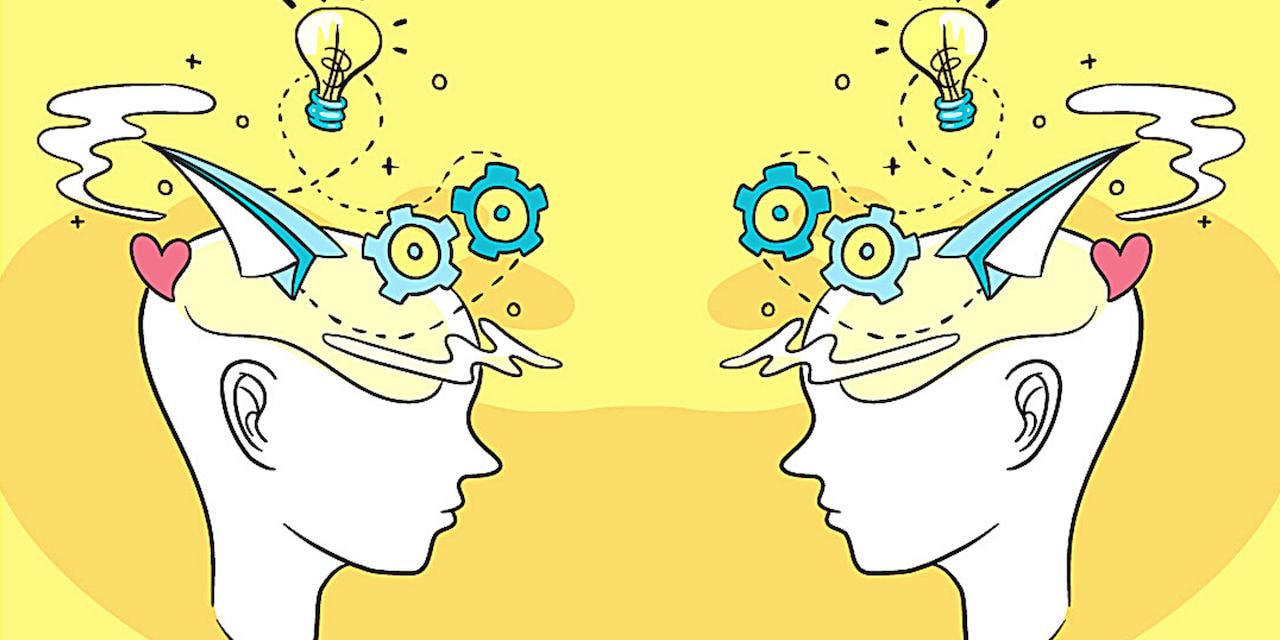
Lalu para petani yang tidak pernah sekolah padahal mampu menyediakan pangan bagi banyak orang itu dianggap tidak pernah belajar dan tak berpendidikan, para pengukir kayu di Jepara, para pematung batu di Muntilan, para pengrajin terakota di Kasongan, penyungging wayang kulit, pembatik dan sebagainya yang telah menghadirkan keindahan untuk dunia juga dianggap tidak berpendidikan dan tidak belajar hanya karena tidak sekolah.
Ternyata pengertian belajar selama ini telah mengalami distorsi yang sangat akut—belajar hanya dipahami sekadar membaca buku serta menghafalkan mata pelajaran karena besok mau ulangan atau hendak menghadapi ujian.
Proses tersebut telah terjadi berabad-abad, beranak-pinak hingga takterasa bahwa kita semua telah terasing jauh dari realitas kehidupan keseharian yang senyata-nyatanya. Kita semua orang dewasamenghabiskan waktu untuk menghafal berbagai macam hal yang nun jauh di antah berantah sana, namun ironisnya malah tidak kenal dengan hal-hal mendasar di lingkungan terdekat kita. Tepatlah peribahasa yang sangat tersohor menggambarkan sistem pembelajaran yang kita alami; “kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak”.
Datanglah pandemi COVID-19 yang meluluhlantakkan seluruhkelaziman yang bernama sekolah. Sekolah harus dipindah ke rumah, orang tua kaget harus menggantikan peran guru, padahal sudah lama tidak terlibat dengan proses belajar anaknya—karena kadhung pasrah bongkokan kepada sekolah. Sementara subyek belajar seolah-olah (atau) dianggap tidak tersedia di sekitar rumah, sumber belajar, nara sumber jauh dari rumah maka tergantunglah dengan alat yang disebut internet, android, dan persoalan baru hadir yakni gangguan signal, internet tak menjangkau hingga beaya pulsa membengkak.
Hal yang terakhir ini, kini menjadi polemik nasional, bahkan dianggap menjadi sumber masalah satu satunya. Mengapa rumah dan sekitarnya tidak dijadikan sumber belajar anak-anak kita?

Sanggar Anak Alam (SALAM) sejak 21 tahun yang lalu menyadari untuk tidak jumawa merasa dirinya hebat, merasa menjadi pusat pengetahuan. Kami meyakini bahwa ekosistem belajar itulah yang harus dibangun sejak dari keluarga masing-masing. Maka posisi SALAM hanyalah media, wadah yang berperan mendinamisir serta menyambung interaksi semua orang yang terlibat. Hal lain yang diupayakan SALAM dalam proses belajar agar tidak mengasingkan anak dari rumah dan lingkungannya yakni, dengan pilihan metode riset sesuai dengan minat dan kontekstual. Maka tidaklah mengherankan jika riset yang mereka pilih objek yang sehari-hari mudah ditemukan, misalnya; tentang asupan harian (sarapan, makan siang, makan malam, kudapan), menyiapkan makan siang di sekolah, mendesain baju, memasak soto, memanfaatkan limbah, mengolah coklat, meriset lingkungan tempat tinggal, membuat dan menjual cilok, memelihara ayam kampung, menanam bayam dll. Melalui riset tersebut anak-anak menemukan pengetahuan yang otentik, objek riset juga dapat menuntun mereka pada keterkaitan dengan pengetahuan lainnya, misalnya; matematika, bahasa, geografi, sejarah, IPA dsb.
Pilihan sistem belajar seperti ini membawa anak belajar secara holistik, mereka sejak dini mengenali struktur berfikir serta memahami sebab akibat. []
Seorang otodidak, masa muda dihabiskan menjadi Fasilitator Pendidikan Popular di Jawa Tengah, DIY, NTT dan Papua. Pernah menjadi Ketua Dewan Pendidikan INSIST. Pendiri Akademi Kebudayaan Yogya (AKY). Pengarah INVOLPMENT. Pendiri KiaiKanjeng dan Pengarah Sekolah Alternatif SALAM Yogyakarta.


Leave a Reply