Sudah bisa dipastikan setiap pergantian Menteri Pendidikan di Indonesia sejak zaman Orde Baru, selalu ada pergantian kebijakan yang terkait dengan sekolah, dan yang paling sering menjadi sasaran adalah perombakan kurikulum. Sejak zaman Orde Baru hingga sekarang telah terjadi empat kali perubahan: antara lain pada tahun 1975, lalu pada tahun 1984 dikenal kurikulum Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), pada tahun 1994 juga terjadi perombakan kurikulum, pada tahun 2004 membahana kembali istilah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), serta Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2006. Tahun ini pemerintah berencana menerapkan kurikulum baru 2013. Dalam Kurikulum 2013 konon ditekankan dalam hal kompetensi dan kreativitas.
Selain kurikulum, juga lahir kebijakan-kebijakan fenomenal yang dapat kita runut kembali, misalnya pada zaman menteri Daoed Joesoef karena dianggap pendidikan Indonesia tidak memiliki visi, maka Daoed Joesoef merumuskan visi pendidikan serta membangun perangkat pendukungnya. Daoed Joesoef terkenal dengan kebijakanya NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan) yang intinya dimaksudkan untuk membersihkan kampus dari kegiatan-kegiatan berpolitik (memisahkan aktivitas ilmiah dari dunia politik). Menurut Daoed, kegiatan politik hanya boleh dilakukan di luar kampus, sementara tugas utama mahasiswa adalah belajar. Dengan kebijakan ini, ia menghapuskan Dewan Mahasiswa (DEMA) di universitas-universitas di seluruh Indonesia, dan praktis melumpuhkan kegiatan politik mahasiswa.
Sejumlah menteri setelah Daoed Joesoef antara lain Nugroho Notosusanto. Pada tanggal 19 Maret 1983, Nugroho dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Pembangunan IV. Ia dikenal sebagai orang yang kaya ide, karena semasa menjadi menteri, ia mencetuskan banyak gagasan, seperti konsep wawasan almamater, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB), Pendidikan Humaniora, mengubah kurikulum, menghapus jurusan di Sekolah Menengah Atas (SMA), sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru (Sipenmaru). Nugroho hanya dua tahun menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, namun melahirkan banyak kebijakan, yaitu Universitas Terbuka (UT) sebagai perguruan tinggi negeri yang paling bungsu di Indonesia. Program Wajib Belajar Orang Tua asuh, dan pendidikan kejuruan di sekolah menengah. Nugroho adalah satu-satunya menteri yang mengeluarkan Surat Keputusan mengenai tata laksana upacara resmi dan tata busana perguruan tinggi. Akan tetapi, sebelum SK ini terlaksana Nugroho telah dipanggil Tuhan Yang Maha Esa.
Selanjutnya Menteri Wardiman Djojonegoro mengintrodusir link and match (kesesuaian dan keterpaduan) yakni sebuah strategi penyelenggaraan pendidikan yang memfokuskan perhatian pada tenaga siap pakai. Link and match merupakan program utama yang dijalankan oleh Wardiman semasa menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Konsep ini sendiri sebenarnya tidak lahir dari pemikiran Wardiman, tetapi diintroduksi dari pendidikan di Amerika Serikat. Prof. Karl Willenbrock, pakar pendidikan dari Harvard University Amerika Serikat, mengusulkan gagasan perusahaan menjadi “bapak angkat” bagi perguruan tinggi. Dalam pemikirannya, perusahaan tidak sekadar memberi tempat berlatih atau menyisihkan sebagian keuntungannya, tetapi juga terlibat dalam pengembangan lembaga pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Dari gagasan inilah kemudian konsep link and match secara luas di dunia pendidikan.
Gagasan ini awalnya berangkat dari indikasi banyaknya lulusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan (lapangan kerja), dari aspek dan jenis keterampilan yang dibutuhkan. Berangkat dari asumsi bahwa dunia pendidikan dan dunia kerja seringkali berjalan sendiri-sendiri. Maka konsep link and match didasari kebutuhan tenaga kerja terampil, serta lulusan sekolah yang memiliki keterampilan yang memadai (sesuai). Karena disinyalir lembaga pendidikan selama kurun waktu sejak kemerdekaan belum mampu memenuhi tuntutan tersebut, konsep link and match, dimasukkan sebagai terapi, untuk mengatasi persoalan tenaga kerja siap pakai. Maka dikembangkan kembali sekolah kejuruan dan disusul dengan serangkaian kerja sama Depdikbud dengan perusahaan-perusahaan serta instansi-instansi yang secara riil menikmati keuntungan, misalnya dalam hal menyediakan tempat untuk magang anak-anak sekolah. Termasuk di dalam rangkaian upaya ini adalah merealisasi 20 persen kurikulum lokal.Dengan kata lain, kebijakan link and match ini merupakan kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dikembangkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan, kebutuhan tenaga kerja, dunia usaha, dan dunia industri.
Di era reformasi, dunia pendidikan kembali diguncang gegap gempita silang sengkarut. Gus Dur membuat kejutan dengan memisahkan bidang kebudayaan dari departemen pendidikan. Barangkali upaya pemisahan ini dimaksudkan agar dalam mengurus pendidikan bisa lebih terfokus. Dari pertimbangan pragmatis memang masuk akal, namun secara subtansial apakah bisa pendidikan dipisahkan dari kebudayaan?
Pada tahun 2008 kembali terjadi gunjang-ganjing karena pemerintah bersikukuh dengan sistem Ujian Nasional (UN) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menjadi kontroversi sampai sekarang. Opini ketidaksetujuan masyarakat sangat jelas, namun sama sekali tidak mempengaruhi kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan UN. Kasus UN telah mempertontonkan pengalaman buruk. Mungkin tidak terjadi di dunia lain bahwa ujian sekolah harus melibatkan aparat keamanan, bahkan lebih memalukan lagi Detasemen Khusus Antiterror 88 menggerebeg rumah guru yang tengah membantu murid-muridnya mengisi form isian ujian. Apapun alasannya, contoh tersebut telah memperlihatkan cara pandang security aparatus pendidikan dalam operasional proses pendidikan.
Belum selesai urusan Ujian Nasional (UN), Mohammad Nuh melansir lagi Kurikulum 2013, perdebatan kembali meruyak baik yang pro dan kontra, dan Mohammad Nuh menjawabnya (Harian Kompas, Kamis, 7 Maret 1013):
“Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang pernah digagas dalam Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004, tetapi belum terselesaikan karena desakan untuk segera mengimplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006. Rumusnya berdasarkan sudut pandang yang berbeda dengan kurikulum berbasis materi sehingga sangat memungkinkan terjadi perbedaan persepsi tentang bagaimana kurikulum seharusnya dirancang. Perbedaan ini menyebabkan munculnya berbagai kritik dari yang terbiasa menggunakan kurikulum berbasis materi. Untuk itu, ada baiknya memahami lebih dahulu konstruksi kompetensi dalam kurikulum sesuai koridor yang telah digariskan Undang-undang Sisdiknas sebelum mengkritik, ungkap Mohammad Nuh”.
Membaca perdebatan Kurikulum 2013, pertanyaan lebih lanjut yang muncul adalah jikalau kita perumpamakan membangun proses belajar mengajar seperti halnya membangun sebuah rumah, apakah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan perlu membuat bestek komplit dan lengkap sehingga tidak memberi peluang bagi siapapun yang akan membangun rumah sesuai kebutuhan, kondisi, dan situasi serta selera? Apakah setiap warga yang menyelenggarakan proses belajar-mengajar harus menggunakan bestek secara murni dan konsekuen? Apa risikonya bagi masyarakat yang tidak memilih bestek Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang didukung dan diperkuat oleh hukum?
Mau kemana arah pendidikan kita? Sementara kita mendapatkan kesan seolah-olah perubahan kebijakan sangat dipengaruhi oleh selera dari latar belakang pendidikan para menterinya, ditambah lagi pengaruh orientasi pasar yang sangat kuat sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada komoditas pendidikan dengan instrumen yang disebut standarisasi dan sertifikasi. Namun kalau kita memandang mundur ke belakang, sesungguhnya hal seperti itu telah terjadi jauh sejak Belanda masih bercokol di Indonesia seperti yang diuraikan berikut ini.
Di bulan September 1983 almarhum Aswab Mahasin pernah melontarkan secara jernih tentang bagaimana perkembangan sekolah yang secara berangsur-angsur mengarah kepada kebakuan―dimulai dengan kutipan Surau Jembatan Besi yang ditulis oleh Hamka;
“tidak ada meja, tidak ada kursi, tidak ada batu tulis, tidak ada kapur tulis. Orang semuanya duduk bersila di lantai…. Ada murid yang telah sekolah di sekolah Gubernemen, dan ada yang bersekolah di Diniyah dan ada yang butahuruf. Ada yang umur 10 tahun dan ada yang berumur 30 tahun, dalam satu kelas”.
Almarhum Aswab mengingatkan saat itu, bahwa Surau Jembatan Besi tengah mengubah dirinya menjadi sekolah dengan sistem kelas. Itulah yang terjadi. Barangkali pada saat itu orang merasa ganjil―demikian juga kesan Hamka yang menuturkannya pada tahun 1951, ketika sekolah juga sudah menjadi sistem yang baku.
Tampaknya pembakuan dan penertiban jagad persekolahan sudah ada sejak dahulu kala. Pada tahun 1905, bahkan untuk mengajar agama-pun orang harus memperoleh izin dari Bupati (Ordonansi Guru, Staatsblad 1905 No.505). Walaupun dua puluh tahun kemudian diperlunak dengan hanya memberitahukan maksud dan tujuan pengajaran, melampirkan daftar murid dan rancangan kurikulum (Stb. 1925 No. 219), tentu hal ini mulai dirasakan sebagai bentuk pengawasan yang memberatkan kalangan pendidik. Pada bulan September 1932, keluar peraturan yang jauh lebih keras lagi: “Semua sekolah yang tidak didirikan oleh pemerintah atau memperoleh subsidi pemerintah diharuskan mengajukan izin terlebih dahulu (Stb. 1932 No. 494). Ada persyaratan yang lebih berat dari sebelumnya; guru-gurunya harus lulusan sekolah negeri atau sekolah bersubsidi―ini syarat yang tidak mudah dipenuhi oleh sekolah-sekolah kebangsaan pada saat itu.
Seluruh pergerakan nasional meradang. Ki Hajar Dewantara secara terbuka mengirimkan telegram kepada gubernur jenderal, bahwa ia akan mengorganisir perlawanan terhadap ordonansi itu. Mohammad Hatta menyerukan agar semua organisasi melakukan aksi massa untuk mendukung pernyataan Ki Hajar. Budi Utomo juga mengancam akan menarik wakil-wakilnya dari Volkstraad, jika ordonansi itu tetap berlaku. Di Yogyakarta, PPKI bersama Muhammadiyah dan Tamansiswa menyelenggarakan rapat raksasa yang dihadiri lebih dari 10.000 orang untuk menentang berlakunya ordonansi itu di wilayah kesultanan dan kesunanan. Dalam kurun waktu sekitar lima bulan, ribuan rapat protes diorganisir di seluruh Jawa dan Sumatera, hingga menarik perhatian seorang John Ingleson untuk menulis, bahwa belum ada isyu yang mampu mempersatukan pergerakan nasional sebelum kasus ordonansi ini. Akhirnya gubernur jenderal de Jonge menyerah. Ordonansi itu dibekukan pada bulan Februari 1933, hanya lima bulan setelah dinyatakan berlaku.
Apakah usaha untuk pembakuan sekolah berhenti setelah dibekukan? Pada saat itu juga berbagai upaya dilakukan oleh penguasa, melalui pengakuan, perangsang (semacam bantuan), juga dilakukan — kalau istilahnya sekarang — pembinaan, di mana senantiasa diupayakan agar sistem yang baku berjalan dan sistem yang dianggap menyimpang terhalang. Dasar-dasar penilaiannya bisa terkait ideologis, atau dengan bahasa pedagogis yang sesungguhnya mengandung kepentingan terhadap urusan ideologis.
Usaha pembakuan masih terus berlangsung, meskipun Indonesia telah merdeka. Sekalipun pada masa penjajahan dirasakan bahwa pembakuan yang dilandasi kepentingan kekuasaan menimbulkan kerepotan, namun tidak serta merta setelah merdeka proses pembakuan berhenti. Masih saja ada ketakutan terhadap penyelenggaraan sekolah yang dianggap menyimpang, tidak memenuhi syarat―bahkan lambat laun berkembang menjadi stigma bagi banyak lembaga sekolah nonpemerintah. Anehnya di sekolah negeri pun usaha pembakuan terus berlanjut dan dirasakan penting. Begitu pentingnya maka setiap kali pergantian menteri selalu diikuti dengan pergantian-pergantian ukuran-ukuran baku, sehingga tampak bahwa sekolah lantas diperlakukan sebagai bengkel uji percobaan.
Perkembangan pembakuan dalam proses berikutnya justru lebih parah, yakni bermetamorfosa menjadi penyeragaman, padahal dalam dunia pendidikan yang satu fungsinya bernama sekolah ada dua fungsi yang tidak bisa dicampuradukkan, dan tidak bisa diseragamkan. Pertama, dunia sekolah yang dibirokrasikan, diundang-undangkan oleh kaum penguasa dengan memiliki kepentingan dan ideologi tertentu. Kedua, jagad proses dan kehidupan nyata yang memiliki elan-vitalnya sendiri, yakni sekolah dipahami merupakan kehidupan nyata, berangkat dari kebutuhan nyata serta proses mencari jawaban atas segala persoalan serta berbagai faktor yang mempengaruhi kehidupan yang dihadapi.
Belajar dari segala zaman, yang tidak pernah berubah adalah cara pandang (paradigma). Ada dua pandangan kuat di kalangan pendidik. Pandangan pertama melihat bahwa pendidikan bagi pihak yang memiliki kekuatan mendominasi selalu digunakan untuk melanggengkan sekaligus menciptakan penguat untuk legitimasi mereka. Maka pendidikan yang dilakukan pada hakikatnya adalah alat untuk melanggengkan sistem dan struktur sosial yang sudah ada. Dalam dunia pendidikan, pandangan seperti ini disebut teori “reproduksi.”
Pandangan kedua, berangkat dari asumsi bahwa manusia terkungkung dalam sistem dan struktur yang melahirkan dehumanisasi, maka proses pendidikan merupakan upaya pembebasan manusia, karena pendidikan merupakan media/sarana untuk kesadaran mengembalikan kemanusiaan atas manusia. Dalam dunia pendidikan, pandangan ini disebut sebagai teori “produksi”.
Tentu saja kedua pandangan itu dalam praktiknya tidak serta merta mudah dilacak bagi mata biasa, karena kedua pandangan tersebut masing-masing selalu menyertakan kemuliaan, juga menonjolkan tujuan kebaikan bagi manusia. Freire secara tegas telah memperingatkan kepada para pendidik tentang bahaya praktik sekolah, yakni suatu proses pendidikan yang dialihkan dari atas atau yang berasal dari luar belaka, bahkan disinyalir bahwa sekolah juga ikut andil dalam penindasan orang miskin serta menciptakan “budaya bisu”, karena melalui sekolah kaum elit dan media massa menyampaikan pandangan hidupnya kepada orang miskin. Akibatnya orang miskin mengambil alih pandangan kaum elit untuk memandang diri mereka―dari situlah lahir “budaya bisu”; orang miskin menjadi bisu dan tak sanggup lagi mengungkapkan aspirasi dan kepentingan mereka yang sebenarnya. Secara tegas Freire menunjukkan relasi sosio-budaya, proses pendidikan seperti itu menuju “dehumanisasi” baik kepada kaum yang menindas maupun kepada kaum yang tertindas. Berangkat dari pengalaman itu, dikembangkan metode penyadaran (konsientisasi) dengan menggunakan media alfabetisasi untuk mencapai jalan keluar.
Bagi para pendidik aliran kedua, dalam urusan proses pendidikan, lebih spesifik lagi yakni sekolah yang didirikan, tidak cukup hanya bicara urusan kurikulum, metode, teknik belajar-mengajar, namun bagaimana mewujudkan prasyarat terbangunnya sistem belajar-mengajar yang tidak terjerumus ke dalam “kubangan dehumanisasi”. Dehumanisasi merupakan anak dari paham filsafat yang bertolak dari kehidupan nyata yang melahirkan pertanyaan: “Mengapa mayoritas manusia menderita, sementara ada pihak yang justru menikmati penderitaan orang lain?”. “Mengapa ada pihak-pihak yang menikmati keuntungan dengan cara-cara yang tidak adil, dan pihak yang menikmati ini justru kelompok minoritas umat manusia?”, serta masih banyak pertanyaan yang muncul karena persoalan penindasan dan ketidakadilan. Padahal ketidakadilan, penindasan atau apapun namanya serta apapun alasannya adalah tidak manusiawi, karena menafikan harkat kemanusiaan―itulah dehumanisasi.
Namun apa yang terjadi? Dehumanisasi bersifat mendua, yakni terjadi dalam diri golongan mayoritas kaum tertindas, tetapi juga dalam diri golongan kaum minoritas yang menindas: keduanya menyalahi kodrat sebagai manusia sejati. Mayoritas kaum yang tertindas menjadi tidak manusiawi karena kemanusiaan mereka dinistakan, karena mereka dibuat tak berdaya dan dibenamkan dalam “kebudayaan bisu” (submerged in the culture of silence). Sedangkan minoritas kaum penindas menjadi tidak manusiawi karena telah mendustai hakikat kemanusiaannya, melupakan keberadaan hati nurani sendiri dengan memaksakan penindasan bagi manusia sesamanya. Maka tidak ada pilihan lain, yakni upaya dan ikhtiar memanusiakan manusia (humanisasi) merupakan tindakan mutlak. Dehumanisasi memang kenyataan yang terjadi dalam sejarah peradaban manusia dan tetap merupakan suatu kemungkinan ontologis di masa mendatang, namun dehumanisasi bukanlah keharusan sejarah. Secara dialektis kenyataan tidak harus menjadi keharusan. Maka menjadi tugas manusia untuk mengubahnya agar sesuai dengan apa yang seharusnya. Itulah fitrah manusia sejati (the man’s ontological vocation).
Sangat gamblang dengan kesimpulan-kesimpulan hasil perdebatan panjang dan terjadi berabad-abad lamanya tentang pendidikan. Walaupun sesungguhnya perdebatan itu terus-menerus mengulang-ulang, mereproduksi pikiran-pikiran yang terjadi sebelumnya. Mari kita simak sebagai catatan, terlepas dari setuju dan tidak setuju, bahkan pada tingkat keberatan terhadap sebuah pandangan atau pemikiran sangat ditentukan oleh cara pandang atau paradigma yang dianut. Dari perjalanan panjang proses jatuh bangun penyelenggaraan proses pendidikan di Indonesia, tokoh perintis pendidikan bangsa Ki Hajar Dewantara mengakui bahwa visi pendidikan yang kita kembangkan sesungguhnya bermuara dari metode modern. Mengapa demikian, alasannya sangat jelas, yakni yang mampu menghadapi hegemoni Barat adalah kaum terpelajar yang lulus dari sekolah-sekolah yang menggunakan metode dari Barat namun tetap berpedoman pada “kebudayaan Timur”. Maka pembentukan karakter, sifat dan sikap dasar budi pekerti menjadi perhatian utama.
Lebih lanjut penting kira kita meneliti apa niat dibalik mendirikan sekolah? Tentu dapat dilacak sejak dari tujuan yang dicanangkan, bagaimana tata laku penyelenggaraannya, bagaimana proses dan pilihan-pilihan metodenya, peran orang tua murid, masyarakat di sekitarnya hingga bagaimana memperlakukan murid sehari-harinya.
Seorang otodidak, masa muda dihabiskan menjadi Fasilitator Pendidikan Popular di Jawa Tengah, DIY, NTT dan Papua. Pernah menjadi Ketua Dewan Pendidikan INSIST. Pendiri Akademi Kebudayaan Yogya (AKY). Pengarah INVOLPMENT. Pendiri KiaiKanjeng dan Pengarah Sekolah Alternatif SALAM Yogyakarta.


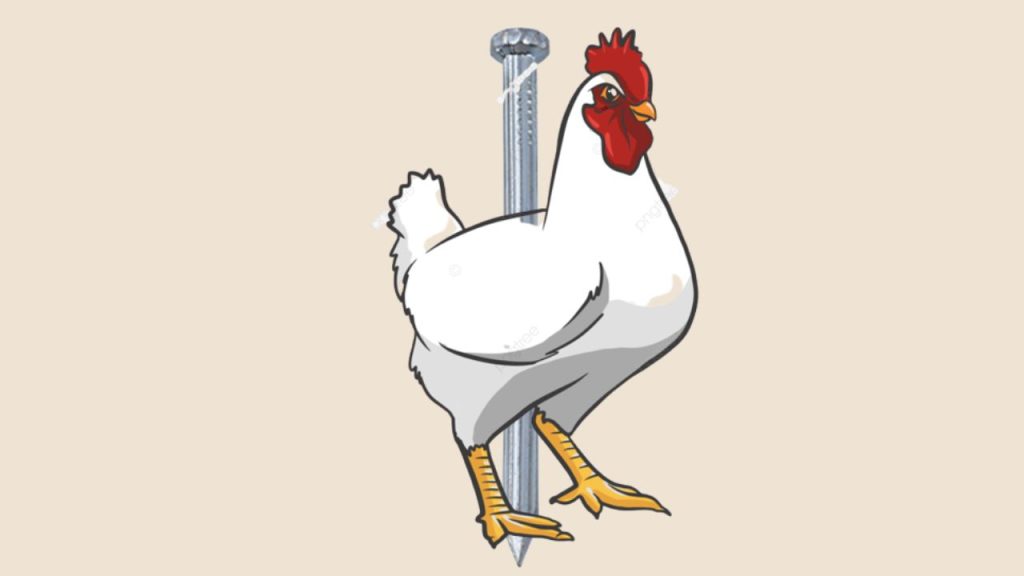
Leave a Reply