
Salah satu yang membuat saya betah saat bertugas di Sokola Rimba, Jambi adalah sikap anak-anak di sana kepada saya. Mereka memperlakukan saya layaknya teman yang setara. Jangankan disapa ‘Pak Guru’, embel-embel ‘Abang’, ‘Kakak’, atau ‘Mas’ di depan nama saya sama sekali tidak ada. Semua orang dari balita yang baru belajar bicara hingga tetua-tetua adat Orang Rimba menyapa saya ‘Faway’. Ini membuat saya nyaman.
Ketika belajar, kami banyak berdiskusi dengan saling menyapa di antara kami dengan memanggil nama. Kadang saya yang mengajar, sering kali anak-anak rimba yang mengajar saya. Saya mengajar untuk pelajaran-pelajaran membaca, menulis, berhitung dari dasar hingga terapan-terapannya. Sedangkan mereka mengajarkan saya banyak hal, mulai dari teknik memasang jerat, membangun rumah sederhana dari bahan-bahan yang tersedia di hutan, tanaman-tanaman obat-obatan, dan beberapa hal praktis untuk hidup di hutan lainnya.
Alasan ini pula yang membuat saya agak kikuk saat pindah tugas di Kabupaten Asmat, Papua. Di sana hampir semua orang menyapa saya dengan panggilan ‘Pak Guru’. Sapaan ‘Pak Guru’ saat di Asmat membuat saya kikuk dan kesulitan untuk berbaur dengan warga Mumugu Batas Batu. Sapaan ‘Pak Guru’ secara tegas sedari awal memberi jarak yang cukup jauh di antara saya dan mereka. Menjadi pembeda, memberikan kesan bahwa di antara kami tidak setara. Ada yang mendominasi dan ada yang didominasi. Sungguh saya tidak suka sekali keadaan seperti ini.
Konstruksi sosial yang terbentuk bahwa yang paling berpengetahuanlah yang bisa berkuasa, yang berjabatan tinggilah yang selalu benar dan memegang kendali menambah rumit masalah.
Beberapa anak memang berhasil menyingkirkan bias hirarki guru-murid di antara kami. Saya Kami bersama pelan-pelan menyingkirkan bias itu. Dengan mereka itulah saya pada akhirnya menjadi sangat akrab. Berbulan-bulan kami berusaha menyingkirkan bias hirarki ini, hanya dengan segelintir orang saja saya berhasil. Kebanyakan malah keberhasilan itu terjadi pada anak-anak berusia di bawah tujuh tahun.
Saya merasa ini adalah salah satu kegagalan selama bertugas di Asmat. Karena hal ini, saya membutuhkan waktu cukup lama untuk bisa benar-benar berbaur dengan anak-anak dan warga Mumugu Batas Batu. Lain halnya saat di rimba. Hanya sepekan saya bisa berbaur dan beradaptasi dan kurang dari dua bulan saya mampu menguasai bahasa rimba. Setidaknya untuk percakapan sehari-hari.
Beberapa hari belakangan, saya membaca berita tentang seorang guru yang menghajar muridnya di sekolah. Kejadian ini terjadi di salah satu sekolah di Pangkalpinang, Bangka Belitung. Guru berinisial M memukuli murid berinisial R berusia 14 tahun. Tindakan ini Ia lakukan karena kesalahan yang tidak sepantasnya dihukum terlalu keras. Begitu setidaknya menurut pandangan saya.
Saya gatal ingin lekas berkomentar, namun memaksa untuk menahan diri karena saya enggan berkomentar jika belum benar-benar paham duduk perkaranya. Kabar terakhir yang saya baca, tindak kekerasan yang dilakukan guru M terjadi karena M geram dengan ulah si murid, Ia menyapa M tanpa embel-embel ‘Pak’. Ia hanya menyapa guru dengan memanggil namanya. Tingkah ini Ia lakukan tidak hanya sekali saja.
Bagi banyak tradisi sehari-hari yang berlaku di negeri ini, apa yang dilakukan murid itu adalah bentuk kekurangajaran, sebuah laku yang sama sekali tidak sopan. Tindakan yang dilakukan murid itu mencederai keyakinan moral dan kesopanan yang disepakati masyarakat. Tentu saya bisa menerima ini dan bisa memaklumi jika murid dinyatakan bersalah.
Tetapi, yang sangat mengusik saya adalah apa yang dilakukan oleh guru M terhadap murid R. Apakah harus seperti itu? harus menghajar si murid dengan pemukulan atas kesalahan yang, bagi saya, tidak layak diganjar dengan hukuman yang begitu keji.
Entahlah, setelah begitu derasnya perubahan di negeri ini, hierarki guru-murid masih begitu disakralkan, masih begitu kaku diterapkan di banyak tempat. Dan, lebih dari itu, guru bisa begitu mudah menghukum sekehendak hatinya.
Dalam kultur yang berkembang dalam dunia pendidikan formal kita, guru memang menjadi begitu berkuasa. Rezim orde baru betul-betul memanfaatkan struktur dan sistem pendidikan yang berjenjang hingga strata paling atas untuk menaklukkan murid-murid yang belajar di sekolah. Untuk menerapkan ini semua, guru menjadi garda terdepannya. Murid-murid di seragamkan, kedisiplinan mutlak ditekankan, dan kepatuhan menjadi sikap yang harus dijejalkan kepada murid-murid. Bukan sesuatu yang aneh di masa orde baru dahulu, murid-murid dengan sepatu yang sedikit berbeda warnanya saja akan dihukum dengan hukuman yang keras. Dengan semua itu, rasa takut menjadi hasil utama yang dibawa murid-murid ke rumah. Takut salah seragam, takut tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah, takut gagal dalam ujian, dan ketakutan-ketakutan lainnya dengan ganjaran hukuman yang membuat trauma.
Bukan berarti saya menganggap tidak penting semua itu, tetapi yang terjadi selama ini memang sudah sangat kebablasan. Beberapa guru yang mencoba sedikit memprotes saja dengan sistem yang semacam itu, akan dikucilkan bahkan dipindahtugaskan ke daerah jauh. Jangankan memprotes sistem yang salah, tidak mencoblos Golkar dalam pemilu saja guru akan mendapat hukuman keras. Sialnya, residu-residu dari pola semacam itu masih berceceran di banyak tempat di negeri ini.
Konstruksi sosial yang terbentuk bahwa yang paling berpengetahuanlah yang bisa berkuasa, yang berjabatan tinggilah yang selalu benar dan memegang kendali menambah rumit masalah. Banyak guru yang memanfaatkan kondisi-kondisi itu untuk berlaku paling kuasa di sekolah. Ini sangat berbahaya karena hegemoni semacam itu membuat para guru bisa gelap mata dan berlaku menindas terhadap muridnya karena dianggap bodoh dan tidak berpengetahuan.
Saya merasa, sudah saatnya kini relasi guru dan murid harus dibongkar total. Guru bukan lagi menjadi pihak yang paling tahu dan berhak melakukan apapun kepada muridnya, dan murid tak lagi semata dianggap sebagai wadah kosong yang bisa diisi dengan apa saja semau guru. Sudah bukan zamannya lagi murid menunduk-nunduk di hadapan guru dan takut setengah mati kepadanya. Relasi guru dan murid bukan lagi antara pengajar dengan yang diajar, tetapi sebagai rekan belajar. Guru memfasilitasi murid untuk berdiskusi meneliti, mengkaji dan menelaah pelajaran bersama-sama. Saling belajar saling mengajar, berdiskusi dan memfasilitasi.
Sebagai penutup tulisan ini, saya akan menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala saya usai membaca berita guru menghajar murid itu. Lalu bagaimana dengan kondisi batin murid-murid lain yang melihat kejadian itu? Saya sulit membayangkannya. Apakah melulu pendidikan harus dekat dengan kekerasan? Apakah laku semacam itu yang hanya mampu mendidik murid menjadi manusia yang bermartabat? Saya mengajak kita semua merenung untuk semua ini. Karena bagi saya, ini terlalu mengerikan.
Sukarelawan di SOKOLA, lembaga yang bergerak untuk memfasilitasi pendidikan bagi komunitas masyarakat adat di Indonesia.
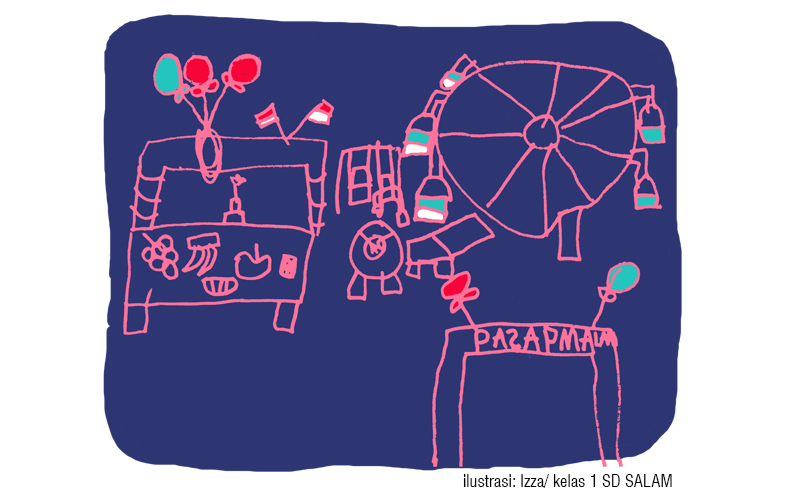


Leave a Reply