Keinginan untuk saling belajar, berbagi, dan menguatkan telah mempertemukan banyak aktivitas pendidikan alternatif selama lebih kurang tiga hari di Yogyakarta, dari 21 hingga 23 Oktober 2016. Kalau saja pendaftarannya tidak dibatasi barangkali akan lebih banyak lagi para pegiat maupun mereka yang penasaran dengan pendidikan alternatif yang datang. Bisa jadi karena memang inilah acara pertama yang secara eksplisit membawa nama Pendidikan Alternatif, diselenggarakan oleh para pegiat pendidikan alternatif, dan untuk pendidikan alternatif.

Mereka datang dari Aceh hingga Papua, dari anak-anak hingga para orang tua. Tak kurang lima puluhan organisasi dan dua ratusan peserta hadir, meramaikan acara hingga akhir yang dihelat di Sanggar Anak Alam (SALAM), Nitiprayan, Yogyakarta. Cerita mereka bisa hadir ke SALAM beragam. Beberapa diniati untuk membangun jejaring dengan sesama komunitas pendidikan alternatif, beberapa lainnya untuk memperluas wawasan mengenai gerakan pendidikan yang kian marak. Salah satu cerita untuk dapat membiayai perjalanan ke acara adalah dengan berjualan kaos, kopi, dan sejenisnya.
Acara yang disebut sebagai Pertemuan Nasional Pendidikan Alternatif ini mengambil tema “Merayakan Kemerdekaan Anak”. Apakah selama ini anak-anak belum merdeka? Atau bahkan tidak merdeka? Jawabnya: ya! Anak-anak belum sepenuhnya merdeka, bahkan belum merdeka dalam memilih tempat mereka belajar, cara mereka belajar, juga hal yang mereka pelajari.
“Begitu anak masuk dalam dunia pendidikan persekolahan, saat itu jugalah anak telah menyerahkan kemerdekaannya dalam memilih materi pelajaran,” ujar salah seorang pembicara pada seminar pembukaan pertemuan.
Lalu, apa maksud “kemerdekaan anak” itu? Rupaya panitia memang tidak berupaya untuk membingkai arti “kemerdekaan anak” dalam satu definisi yang pasti. Sejak hari pertama panitia sudah mengenalkan berbagai perspektif teoretik maupun pengalaman praktis pendidikan alternatif. Pada seminar pembukaan yang dipandu oleh Jimmy Ph. Paat, dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang mendalami pedagogi kritis, para pembicara yang dihadirkan jelas membawa perspektif yang beragam.

Ki Siswanto dari Taman Siswa misalnya membawa pemikiran pendidikan kritis yang merupakan tafsirannya atas praksis pendidikan Ki Hadjar Dewantara. Upaya yang sama dilakukan oleh H.A.R. Tilaar melalui beberapa karyanya, antara lain “Sowing the Seed of Freedom: Ki Hadjar Dewantara as a Pioneer of Critical Pedagogy” (2014). Romo Setyo Wibowo dari Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara membawakan filsafat pendidikan Jacques Ranciere dengan konsepnya yang kontroversial bahwa “guru yang baik adalah yang tidak tahu, hingga pengetahuan dipelajari bersama-sama, dan siswa harus dipandang setara dengan guru.” Saya sendiri membawakan artikel singkat yang berjudul “Kesadaran akan Keragaman Kebutuhan Pendidikan dan Jenis Praksis Pendidikan”.
Pembicara lain, Aripin Ali dari Sekolah Hikmah Teladan, Bandung, bercerita mengenai sekolahnya yang tanpa seleksi, tanpa sanksi bagi siswa yang bersalah, dan tidak mengurusi soal karakter siswa. Gus Irwan Masduqi, dari pondon pesantren Salafiyah Mlangi, mengenalkan praktik pesantren yang humanis, termasuk dalam memberi sanksi maka jenis hukuman bagi santri tidak dipaksa, melainkan santri sendiri yang memilih. Terakhir Bu Wahya dari SALAM selaku tuan rumah bercerita mengenai praktik pembelajaran berbasis riset yang dilakukan anak-anak di SALAM.

Semua memberikan keragaman perspektif teoretik dan juga praktik pendidikan. Kata kunci pada pertemuan jaringan pendidikan alternatif kali ini barangkali selain “memerdekakan anak” adalah “keragaman”. Barangkali banyak yang tak paham apa yang dikemukakan oleh Romo Setyo melalui filsafat pendidikan dari Jacques Ranciere, atau kesulitan bagaimana membayangkan praktik pendidikan ala Ki Hadjar di era sekarang sementara Taman Siswa sendiri sebagai lembaga pendidikan kian tak ada bedanya dengan sekolah lainnya. Dari Sekolah Raya bahkan terang-terangan tak sepakat dengan Aripin bahwa sekolah tak usah mengurusi karakter siswa, karena Sekolah Raya memang sehari-hari mendampingi anak-anak jalanan yang karakternya belum terbentuk baik.
Menarik melihat keragaman perspektif maupun praktik pendidikan tersebut. Namun pertemuan ini tak hendak mengurusi mengenai bentuk baku praksis pendidikan alternatif. Walaupun pertemuan ini salah satunya bertujuan untuk menegaskan paradigma pendidikan alternatif, namun orientasi untuk merangkul dan membangun jejaring yang lebih kuat lebih diutamakan. Hingga pada pertemuan kecil di komisi A mengenai dasar filosofi, B mengenai manajemen organisasi dan keberlanjutan jaringan, maupun C mengenai respons terhadap kebijakan pemerintah, keragaman tersebut justru menjadi pemerkaya pandangan dan wawasan bersama.
Diskusi yang menarik terjadi pada soal apakah praksis pendidikan yang memerdekakan hanya dapat dilakukan melalui pendidikan alternatif? Atau bisa jugakah dilakukan dalam pendidikan formal?
Menurut hemat saya pendidikan formal memang berkarakter formal yang cenderung membatasi kemerdekaan anak dalam belajar. Sekolah yang ada di masyarakat kita sekarang ini kurikulumnya dibuatkan oleh Pemerintah Pusat, hingga bukan hanya siswa yang tak merdeka, guru pun tak boleh mengubahnya. Mengubah berarti memelencengkan materi dan praktik belajar dari tujuan pendidikan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Walau begitu sejatinya bisa saja pendidikan yang memerdekakan anak dilakukan di sekolah, asalkan konsep, pengertian, juga sistem dan tata kelola sekolahnya fleksibel.
Satu hal yang menurut hemat saya perlu dipikirkan lebih jauh adalah bagaimana menggarap dimensi keilmuan dari gerakan pendidikan alternatif. Hal ini penting menggingat banyaknya pengalaman praktik mengembangkan pendidikan alternatif akan sayang jika sekadar dibagi-bagi sebagai pengalaman belajar. Pengalaman tersebut perlu dipahami, direfleksikan secara kritis, dikaji, hingga menjadi satu rumusan ilmu yang kuat pijakan praktiknya. Inilah Praksis, yakni menautkan antara teori dan praktik, menjadikan praktik sebagai bahan baku membangun kerangka teoretis keilmuan, dan sebaliknya mempraktikkan satu hal dengan didasari oleh basis teoretik yang kokoh.

Harapannya, pendidikan alternatif tidak hanya kuat jaringan solidaritasnya, melainkan juga kokoh kerangka keilmuannya. Di mata pemerintah yang lebih banyak mendengar apa kata para akademisi kampus, tentu ketika Pendidikan Alternatif menjadi bidang kajian keilmuan yang banyak dikaji, diteliti, dan dikembangkan, akan kian menjadi pembanding yang imbang dengan pendidikan formal/persekolahan (schooling system).
Terlepas dari itu, gegap gempita pertemuan jaringan pendidikan alternatif di Nitiprayan, Yogyakarta ini membuat saya sepakat bahwa gagasan Deschooling Society yang dibawa oleh Ivan Illich (1971) puluhan tahun lalu barangkali sekarang makin relevan. Yakni ketika internet dan berbagai perangkat teknologi digital telah berkembang pesat dan melayani kebutuhan seseorang. Termasuk kebutuhan untuk belajar yang kian mudah diperoleh di dunia maya, kapanpun dan di manapun, asalkan ada sinyal internet dan colokan listrik.
Dosen Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang (UNNES), pegiat Rumah Buku Simpul Semarang (RBSS)

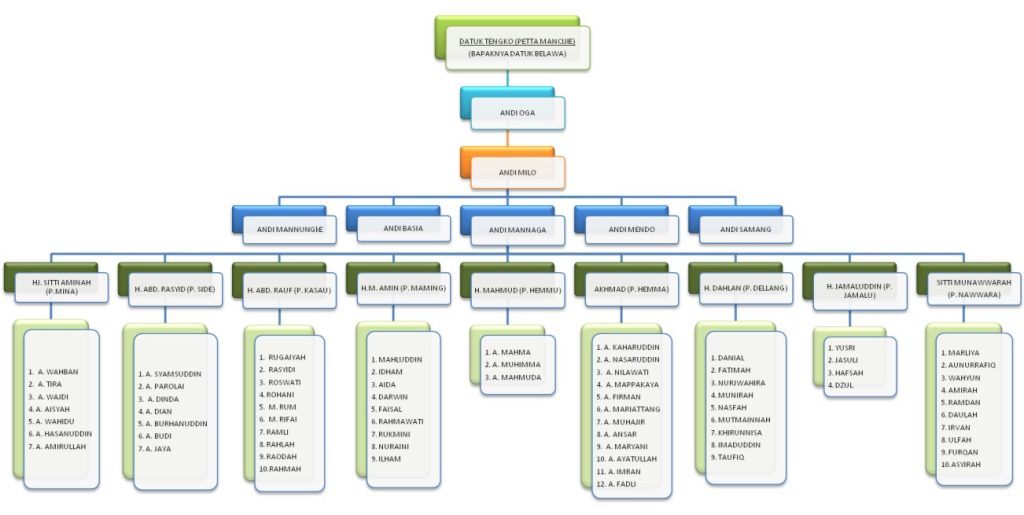

Leave a Reply