Pendidikan tidak sepenuhnya seperti teori tabula rasa yang Jhon Locke katakan. Pendidikan, pada dasarnya bukanlah sekadar penanaman atau pengisian, melainkan aktualisasi potensi siswa. Sejak berabad yang lalu, Plutrach dengan puitis menyatakan, “Pikiran bukanlah bejana untuk diisi, tapi api untuk dinyalakan.” Di zaman modern, Paulo Freire menolak apa yang disebutnya sebagai banking concept of education. Dalam paradigma banking, pendidikan seperti kegiatan menabung. Murid dianggap sebagai ‘celengan kosong’ dan guru sebagai penabungnya. Dalam konsep pendidikan ‘gaya bank’, guru bertindak seperti orang yang berpengetahuan dan murid sebagai orang yang tidak tahu. Guru sebagai subyek dan murid sebagai obyek.

Konsep seperti ini jelas membuat belajar bukan menjadi proses belajar yang sebenarnya, tapi hanya proses pengajaran saja. Kemudian, yang terjadi hanyalah proses transfer ilmu dari seorang guru. Sedangkan, murid cukup menerima, menulis dan menyimpan materi pelajaran. Pendidikan ‘gaya bank’ menganggap pengetahuan sebagai hibah yang diberikan oleh seorang guru kepada para murid.
Dampaknya, murid terhambat untuk mengeluarkan segala potensi yang dimilikinya karena ruang gerak meraka sangat terbatas. Menurut Freire, proses pembelajaran yang demikian sangat tidak manusiawi. Sayangnya, konsep seperti ini, disadari atau tidak, dominan dalam pendidikan kita.
Ruang Dialog
Untuk mengatasi masalah ini, pendidik perlu membuang jauh-jauh pola komunikasi yang monologis dan menggantinya dengan pola komunikasi yang dialogis selama proses pembelajaran. Ruang-ruang dialog dapat bersemi jika interaksi antara guru dan murid didasarkan pada kesetaraan. Karena dialog tidak akan terjadi dalam hubungan yang bersifat dominasi. Dialog dapat terjadi ketika pemikiran kritis dilibatkan dan tidak ada dikotomi antara guru dan murid. Ketika hubungan antara guru dan murid “setara”, maka terciptalah interaksi yang humanistik.
Interaksi humanistik adalah sebuah pola hubungan antara guru dan murid dalam proses pembelajaran yang mengedepankan sikap kesantunan dan saling menghormati. Guru menciptakan suasana yang demokratis dan transparan dalam proses belajar. Guru berusaha mengeliminasi kecenderungan otoriter, sikap ketertutupan dan keangkuhan.
Sedangkan bagi murid, public sphere meminjam istilah Jurgen Habermas, yang telah difasilitasi oleh guru akan dapat mendorong para murid mengeluarkan keaktifan, kemandirian, dan keinovatifan mereka. Setiap individu mempunyai porsi sama dalam menyampaikan pendapat dan dijamin kebebasannya.
‘Pendidikan hadap masalah’ dalam bahasa Freire, merupakan pendidikan yang menuntut keterlibatan. Guru belajar dari murid dan murid belajar dari guru. Guru dan murid sama-sama menjadi subyek yang disatukan oleh obyek yang sama. Guru menjadi rekan murid yang menciptakan kondisi edukatif, melibatkan diri, memotivasi dan merangsang daya pemikiran kritis murid. Kedua belah pihak bersama-sama mengembangkan kemampuan untuk mengerti dan memahami. Maka, dialog menjadi unsur penting dalam proses pendidikan ‘sederajat’.
Pembelajaran Autentik
Usaha berikutnya yang dapat dikembangkan oleh guru adalah bagaimana menciptakan proses belajar yang alami. Semua kurikulum, baik standar isi, proses, maupun penilaian harus bersifat autentik. Artinya kurikulum harus diarahkan pada proses membekali anak dengan kompetensi yang betul-betul dibutuhkannya dalam kondisi real ketika kelak mereka mengambil peran di masyarakat.
Model pembelajaran autentik akan menjadikan kompetensi-kompetensi sebagai sasaran dari setiap elemen dalam sebuah kurikulum. Materi-materi kompetensi yang bersifat akademis, dikejar penguasaanya secara akademis. Sedangkan untuk bahan-bahan yang lebih bersifat afektif atau psikomotrik harus dirancang sedemikian rupa sehingga kompetensi tetap dalam domain yang sama.
Sebagai contoh, dalam bidang Bahasa, seyogianya keberhasilan tidak dilihat dari tolak ukur kemampuan murid dalam penguasaan tata bahasa secara teoritis, namun sejauh mana kemampuan murid dalam membaca, memahami, menulis, dan mengapresiasi suatu karya. Karena, fungsi konkret dari pelajaran bahasa adalah menjadikan bahasa sebagai alat komunikasi dengan berbagai variannya.
Contoh lain, jika dalam pelajaran olahraga, kompetensi sebaiknya tidak diukur secara akademis, seperti kemampuan menghafal nama-nama gerakan dalam olahraga. Tapi, sebaiknya dilihat dari praktik olahraga secara langsung. Karena, di dunia nyata, keterampilan seseorang dalam berolahraga akan dinilai dengan cara tersebut.
Dalam paradigma Multiple Intelligence, kecerdasan manusia tidak terbatas pada single factor IQ, tetapi meliputi sedikitnya membilan kecerdasan. Matematika, linguistik, spasial, musikal, naturalis, kinestetis, intrapersonal, interpersonal, dan eksistensial. Seorang guru harus mampu melihat murid dengan segala macam keunikannya dari berbagai sudut pandang kecerdasan.
Hingga semuanya harus dilihat relatif dan subyektif. Jika ini menjadi kesadaran guru, tentu tak ada lagi pembedaan Si A anak pintar, sedangkan Si B anak bodoh. Oleh karena itu, sistem perankingan yang memperetegas praktek dehumanisasi dalam pendidikan sudah saatnya ditinggalkan.
Pendekatan Kontekstual
Pembelajaran kontekstual pada dasarnya menyarankan agar murid dibekali ilmu dengan bahan-bahan ajar yang relevan dengan situasi sehari-hari yang mereka alami. Selain anak didik diajarkan sesuatu yang memiliki relevansi dengan kenyataan yang mereka hadapi dalam masyarakat di lingkungan mereka, murid juga akan merasakan keterhubungan mata pelajaran dengan realitas.
Di samping itu, mereka juga memiliki kerangka konkret ilmu yang mereka serap. Dengan cara ini bahan ajar juga lebih mudah terinternalisasi sekaligus terobyektifikasi dengan murid, bukan sekedar menempel dan terlepas sewaktu-waktu. (Haidar Bagir: 2019)
Saya sering membayangkan betapa luar biasanya jika konsep pendidikan kita memperhatikan pendekatan kontekstual ini. Anak-anak pesisir dibekali pengetahuan tentang ‘sosiologi pesisir’, ilmu perikanan dan kelautan, teknologi terapan yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya yang ada di laut dan pantai. Begitu juga anak-anak pedesaan yang memahami “sosiologi pedesaan’, ilmu pertanian dan perkebunan berbasis teknologi yang efisien dan ramah lingkungan. Atau anak-anak perkotaan yang tidak gagap melihat peradaban metropolis karena telah mengenal apa itu ‘sosiologi perkotaan.’
Keseragaman kurikulum bukan berarti buruk, tentu ada kebaikannya. Dengan standar kurikulum yang sama, pemerintah sedang berusaha memastikan tidak terjadi kesenjangan pendidikan dari Sabang sampai Merauke. Namun, keseragamaan akan njomplang jika meninggalkan aspek ‘kearifan lokal’.
Saya teringat ketika SD dulu, belajar di bawah rezim yang gandrung dengan kemonolitikan, ada konsep yang ditanamkan kepada kita semua bahwa makanan pokok bangsa Indonesia adalah nasi. Bisa dibayangkan betapa fatalnya konsep ini jika menjadi common sense anak-anak yang secara tradisi menjadikan sagu, singkong, atau jagung sebagai makanan sehari-harinya.
Berbasis Proyek
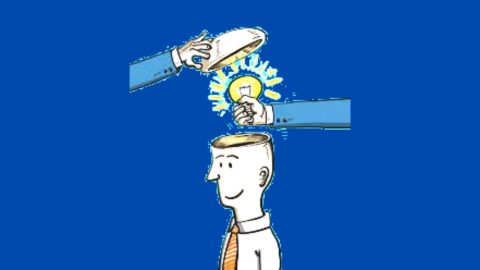
Melalui pembelajaran berbasis proyek, guru dapat menciptakan iklim belajar yang bersahabat bagi murid. Pembelajaran ini benar-benar mendorong inisatif siswa. Seperti namanya, pendekatan ini merancang proses pembelajaran agar sedapat mungkin menjadi simulasi dari dunia nyata.
Dalam pendekatan ini, siswa dididik untuk mengidenifikasi dan merumuskan masalah, mencari berbagai kemungkinan pemecahan secara kreatif, melakukan analisis secara logis, melakukan penelitian jika diperlukan. Untuk akhirnya dapat sampai pada pemecahan yang paling sesuai. (Haidar Bagir: 2019)
Dalam pembelajaran ini, murid dilatih berpikir mandiri, mengembangkan kepercayaan diri serta belajar bekerja dalam tim. Ini sebabnya, pembelajaran berbasis proyek disebut sangat sesuai untuk mengajarkan keterampilan-keterampilan abad ke-21. Paradigma kompetisi saling megalahkan dalam dunia pendidikan sudah saatnya kita minimalisir.
Di era digitalisasi global, kesuksesaan seseorang tidak lagi semata-mata ditentukan karena memenangkan ‘kompetisi’. Faktor yang jauh lebih besar mendorong seseorang mencapai puncak kesuksesaan adalah kemampuan melakukan ‘kolaborasi’. Finlandia, kiblat terbaik pendidikan, sudah sekian tahun yang lalu mendorong para siswanya untuk memiliki kemampuan berkolaborasi, dibanding kemampuan berkompetisi dalam arti yang sempit.
Sudah saatnya para guru melampaui ‘gaya bank’ dalam pendidikan kita. Ada meme yang patut direnungkan oleh seluruh guru di Indonesia:
“Jika Anda menjadi guru hanya sekedar mentransfer pengetahuan, maka ada saatnya Anda tidak akan dibutuhkan lagi. Karena nyatanya, Google lebih cerdas dan lebih tahu banyak hal daripada Anda. Namun jika anda menjadi guru yang mentransfer adab, akhlak, ketakwaan, dan keikhlasan, Anda akan selalu dibutuhkan. Karena google tak memiliki itu semua.”
Redaksi Asumsi – Fajrul Islam Ats-Tsauri
SALAM (Sanggar Anak Alam), Laboratorium Pendidikan Dasar, berdiri pada tahun 1988 di Desa Lawen, Kecamatan Pandanarum, Banjarnegara.



Leave a Reply