Kesadaran Emansipatoris
Dimensi filsafat yang merekonstruksi pemahaman epistemologis antara manusia dan lingkungan hendaknya dialamatkan pada titik pembebasan (emansipatoris). Letak aksi konkret di dalam praktik kehidupan masuk ke ranah ini. Kesadaran emansipatoris, selain diejawantahkan secara praktis sebagai laku, seyogianya juga dipertimbangkan oleh pemerintah melalui kebijakan strategisnya di level nasional.
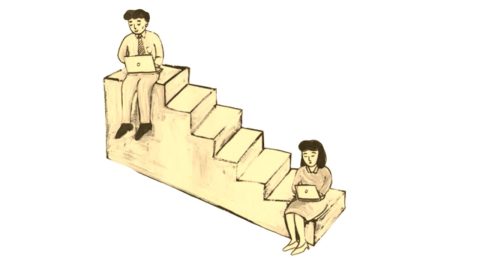
Pembebasan berarti “membongkar” narasi-narasi eksploitatif alam yang dilakukan atas kesempitan epistemologis manusia. Titik tolak filsafat menjadi bangunan mayor yang harus dikokohkan agar ia tak kehilangan orientasi aksiologis ketika bersemuka dengan lingkungan selaku subjek.
Pengobjekkan lingkungan atas kuasa subjek-manusia sudah terbukti memberi dampak negatif. Sisi positif dalam rangka mencari benang merahnya, secara singkat, adalah memosisikan lingkungan sebagai subjek yang hidup sebagaimana memandang makhluk hidup lainnya.
Lingkungan pada gilirannya akan merasa “terhidupkan” dan “menghidupi” manusia serta makhluk lain. Sudah seharusnya bentuk relasi antara dua komponen alam tersebut berlaku dan ditegaskan kembali dalam rangka keseimbangan ontologis.
Yang paling menentukan pula, selain subjek di luar pemerintahan, adalah pemegang regulasi di ranah pusat. Ia laksana pemilik otoritas untuk menjaga kotak pandora yang berisi keputusan-keputusan strategis di mana dan bagaimana nasib lingkungan. Bila pemerintah masih membawa panji-panji pembangunan yang eksploitatif di arena lingkungan hijau jangan harap kalau keputusan itu akan menjadi bumerang bagi mereka sendiri.
Peran konstitusi yang objektif harus menengahi “perselingkuhan” pemerintah dan korporasi manakala lingkungan menjadi basis legit pengerukan yang berorientasi finansial. Masalah ini, kalau dibiarkan, akan menjadi senoktah penyesalan di kemudian hari. Bukan semata oleh pelaku, melainkan anak-cucu di kemudian hari.
Bahasa Indonesia dan Budaya Siber
Penting meneroka perubahan mendasar cara berkomunikasi kita di era Revolusi Industri 4.0. Bagaimana pun juga, di tengah transformasi itu, bahasa Indonesia berperan signifikan sebagai media komunikasi yang niscaya membentuk dan terbentuk karena adanya ruang publik (maya) baru.
Kita acap takjub kurang-lebih satu dekade terakhir manakala internet memberi peluang besar bagi cara berkomunikasi manusia. Era surat-menyurat sudah lama ditinggalkan, memori akan warung telepon (wartel) beranjak gulung tikar, dan kini masuk pada eksklusivisme komunikasi berbasis perorangan—tiap orang memegang telepon pintar, tiap personal bebas berselancar mengarungi dunia ‘antah’ tanpa terikat ruang dan waktu.
Teknologi informasi dan komunikasi mengondisikan khalayak untuk mencapai demokratisasi komunikasi tanpa demarkasi status ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun pendidikan. Jamak orang di dunia kini sedang berada dalam lanskap selebrasi ketika berinteraksi jauh lebih mudah, cepat, dan murah. Keadaan ini, disadari atau tidak, ternyata mengubah secara total pola komunikasi dan tata peradaban kita.

Bila menyibak pandangan epistemologis pola komunikasi di era disrupsi ini, terdapat pertanyaan menarik, yakni sejauh mana kedudukan bahasa Indonesia di tengah posisi itu? Masihkah ia mendapat ruang sebagaimana semestinya seperti beberapa dekade silam tatkala ‘komunikasi tradisional’ masih dikondisikan sebagai bahasa yang baik, benar, maupun indah ala pemerintahan Soeharto?
Posisi Ambivalen
Kaburnya batas-batas komunikasi di jagat maya memberi ruang kontestatif bagi bahasa Indonesia. Posisi ini mengandaikan bahasa Indonesia juga terkena dampak atas medan pertarungan dengan bahasa-bahasa internasional lain. Katakanlah bahasa Inggris yang kerap membuat ketar-ketir para pemerhati maupun akademisi linguistik: apakah bahasa Indonesia bertekuk lutut terhadap bahasa Inggris sehingga eksistensinya tergerus maksimal bila melihat keserampangan pengguna media sosial dewasa ini yang mengarah pada ‘bahasa gado-gado’ itu?
Ini pertanyan klise dan sering diulang terus-menerus pada tiap kesempatan seminar bahasa Indonesia di mimbar akademik. Senjakala bahasa Indonesia makin menunjukkan titik nadir jika menengok realitas penggunaannya. Kosakata hingga kalimat (sintaksis) diporakporandakan oleh warganet tanpa menyadari kalau kecenderungan semacam itu melanggar tatanan bahasa yang ‘baik dan benar’ seperti termaktub eksplisit di undang-undang kebahasaan berikut regulasi praksis versi badan bahasa.
Khalayak lebih rajin dan gemar menggunakan istilah bahasa Inggris karena dianggap mampu mendongkrak ‘status sosial’ lewat percakapan—suatu realitas sosial-kemasyarakatan yang sedemikan khas bagi negara-negara bekas kolonial. Superioritas bahasa Inggris ternyata masih mengakar kuat di benak masyarakat bukan karena semata-mata salah orang itu, melainkan ia dikondisikan demikian atas pengaruh psikologis secara turun-temurun.
Ranah pendidikan sebetulnya bertanggung jawab terhadap penguatan bahasa Indonesia sebagai suatu konsep teoretis maupun praktis di lapangan. Selama ini pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah masih belum sepenuhnya meninggalkan paradigma ‘belajar tentang bahasa’ alih-alih ‘berbahasa’ itu sendiri. Akibatnya, peserta didik tak mendapat kesempatan pegembangan diri secara sistematis dan komprehensif di kelas.
Sekolah sebagai ‘kawah candradimuka’ tempat persemaian dan pendampingan bibit-bobot-bebet peserta didik mesti ditotalkan kembali dalam rangka penginternalisasian bahasa Indonesia di tataran akademik. Ikhtiar ini merupakan usaha diskursif yang paling menonjol di ranah pendidikan. Meskipun di luar dinding kelas, pengonstruksian peserta didik tak lagi otoritas sekolah, tetapi lingkungan sosial yang penuh destruksi pragmatis.
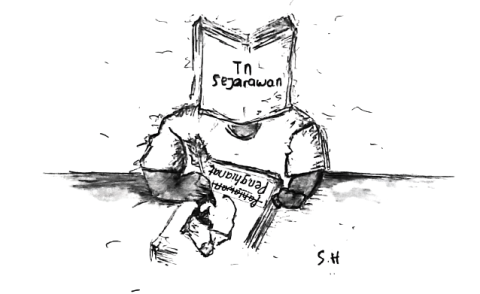
Daulat Subjek
Di luar pengaruh-pengaruh eksternal yang mengondisikan subjek dalam memggunakan bahasa Indonesia, seakan tak ada ruang bebas untuk bergerak kecuali titik koordinat kedaulatan diri sendiri. Posisi kedaulatan dalam konteks penggunaan bahasa Indonesia di jagat maya sedemikian penting, terutama berkelindan dengan ‘merawat’ hasil kebudayaan setelah Sumpah Pemuda itu.
Tiap individu memungkinkan menjadi agen yang aktif-reaktif melalui percakapan bahasa Indonesia, baik pada ragam formal, nonformal, maupun informal. Semua konteks penggunaan bahasa itulah yang hendaknya dikuatkan kembali secara sadar oleh jamak orang. Pada ruang maya, penggunaan bahasa tak sekonyong-konyong urusan ‘baik dan benar’ karena dua poin ini menginduk ragam formal.
Bahasa Indonesia tak boleh dipersempit manifestasi geraknya sehingga melahirkan sikap pesimisme akut seperti halnya digelisahkan ‘polisi bahasa’ selama ini. Bahasa Indonesia merepresentasikan pusparagam parole (ucapan) yang begitu bebas ‘normatif’—sementara kita selalu melihat bahasa hanya urusan langue (sistem bahasa) yang begitu positivistik meski pada aras demikian kita tak bisa mengelak dari aturan permainan bahasa yang telah dipatenkan itu. [] bersambung…….
Peneliti Pendidikan, Penulis Buku Genealogi Hoaks Indonesia


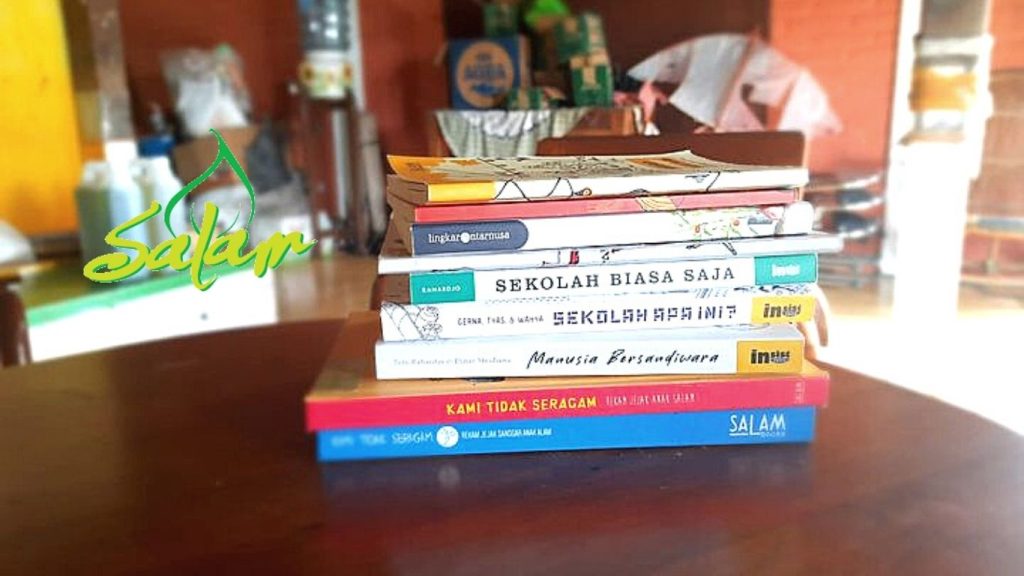
Leave a Reply