Peta Pikiran
Terdapat ungkapan terkenal yang dituliskan Haruki Murakami dalam novelnya bertajuk Norwegian Wood (2000), “If you only read the books that everyone else is reading, you can only think what everyone else is thinking.” Makna intrinsik dari pernyataan Haruki ini bisa dibagi dalam dua perspektif (a) bacaan mempengaruhi pikiran seseorang dan (b) harus membaca lebih banyak ketimbang orang lain agar pikiran kita melampaui orang lain.

Dua interpretasi bebas ini menegaskan betapa kecakapan membaca bisa mengubah, membentuk, dan mengonstruksi pikiran serta sikap seseorang. Hal demikian wajar karena bacaan menawarkan “dunia kemungkinan” yang ditawarkan penulis meski ia tak menyadari akan implikasi ini. Itu kenapa semakin banyak seseorang membaca, ia niscaya memiliki alternatif “kemungkinan” dan “pikiran” yang bisa diteladani dalam menjalani hidup. Secara psikologis orang yang rajin membaca, terutama mengontemplasikan hasil bacaan—memiliki kedewasaan yang lebih ketimbang mereka yang malas, bahkan absen, mendaras. Titik puncak dari kedewasaan itu ialah kebijaksanaan. Ia tak lagi kagetan dan gumunan ketika melihat lapis kebenaran yang dimiliki orang lain. Pembaca yang kuat dan serius, dengan kata lain, cenderung fleksibel merespons realitas kehidupan.
Indonesia hari ini dipenuhi kebencian sektoral hanya karena tersulut perbedaan sepele. Segala friksi apa pun yang sebetulnya bermuara pada kebencian personal maupun kelompok adalah produk dari individu yang tak pernah membaca. Dengan begitu, membentuk tradisi membaca secara total akan mendidik masyarakat sipil untuk bersikap bijaksana. Seharusnya momen hari buku sedunia dihayati pada titik ini.
Ilusi Teknologi Perangkap Revolusi Industri 4.0
Dentuman ilmu pengetahuan terapan pada tiap ranah membawa konsekuensi logis tertentu berikut implikasi jangka panjangnya. Pendidikan dalam konteks formal (sekolah) turut terseret narasi modernitas yang membopong beban otomasi dan digitalisasi. Era disrupsi, demikian khalayak abad ke-21 mengatakan, membawa serangan eksplisit di jagat pendidikan. Terutama seputar orientasi dan kontestasi pembelajaran.
Pihak yang mengurusi regulasi pendidikan pusat kemudian merespons dengan tegas dan lekas agar pendidikan formal menyiapkan diri sebelum dikondisikan zaman. Sasaran pragmatik seperti kecakapan kerja di lapangan tiba-tiba dinomorsatukan sebagai tujuan utama sekolah maupun perguruan tinggi.
Makna pendidikan lambat-laun mengikis sebatas kesiapan lapangan. Filsafat pendidikan juga berubah menjadi kerja, kerja, dan kerja. Wilayah pendidikan dianggap seksi untuk membentuk manusia. Maka tak mengherankan bila manusia modern, anak zaman Revolusi Industri 4.0, dicetak sedemikian rupa guna mengisi pos-pos industri. Sekolah berperan signifikan untuk menyiapkan insan-insan pengekor disrupsi itu.
Kurikulum nasional dibonsai agar kualitas manusianya memenuhi harapan dunia kerja. Pendeknya, sekolah diposisikan sama dengan laboratorium menuju kerja. Dogma ini dipatenkan terus-menerus melalui produksi wacana, “Bangsa kita tertinggal dan harus mengejar ketertinggalannya.”
Belum terserap ke dunia kerja, anak didik cetakan sekolahan itu sudah dibentak misi utopis: kelak manusia segera tergantikan dengan kehadiran robot. Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan dimitoskan total guna menggeser tenaga manusia. Mitos ini mewujud ke dalam sistem dan instrumen praktis yang menginduk pada teknologi mutakhir. Bentuknya bisa beraneka rupa dan ditengarai lebih fantastis ketimbang manusia yang memiliki kecerdasan natural.
Perkuliahan atau pembelajaran jarak jauh salah satunya. Sekolah hingga perguruan tinggi turut merayakan selebrasi atas nama efisiensi transfer pengetahuan. Melegitimasikan metode ini ternyata juga dianggap pro terhadap kemajuan. Sekalipun ia baru diraih oleh institusi pendidikan yang unggul secara finansial.

Amnesia Filsafat Manusia
Tren disrupsi membawa konsekuensi logis terhadap perubahan pola pembelajaran. Titik balik ini acap membayangi setiap transformasi yang diakibatkan oleh revolusi industri. Bila ditengok tiga gelombang revolusi teknologi sebelumnya, ia membawa tekanan sekaligus destruksi masing-masing.
Sebelum ilmuan menemukan komputer, semisalnya, manusia masih berdaulat atas kemampuan menulis secara manual. Kesalahan ketik cukup disadari dengan baik. Kecenderungan salin-tempel hampir absen karena fitur demikian tak ditemukan pada mesin ketik tradisional. Namun, aktivitas semacam itu kini berubah drastis. Akurasi dan konsentrasi tulis-menulis tak setajam generasi lampau. Mereka dilenakan atau dimanjakan oleh pelbagai fitur otomatis yang dihasilkan teknologi.
Teknologi meniscayakan sisi positif dan negatif yang saling beririsan. Ia juga bisa menjadi bumerang bagi kreativitas manusia tatkala teknologi itu diposisikan sebagai alat bantu primer. Determinasi teknologi, dengan kata lain, mampu meremukkan daya kreatif yang bersumber pada kepercayaan natural manusia. Albert Camus menyebut kondisi ini sebagai krisis akut atas ketergantungan peranti artifisial.
Persoalan fundamental dunia pendidikan di setiap jenjang manakala menyikapi gelombang teknologi antara lain disorientasi epistemologis: bagaimana mengawal orientasi aksiologis pendidikan Indonesia tanpa durhaka terhadap nilai filsafatinya. Pandangan ini dikemukakan agar ia tetap mengikuti disrupsi teknologi secara cair tapi sekaligus masih mengakar pada konsep Ki Hadjar Dewantara yang mendudukan manusia sebagai subyek utama.
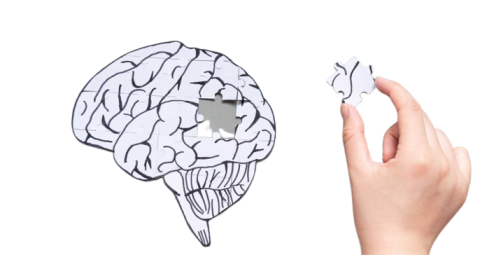
Membangun manusia tak boleh luput dari tujuan pendidikan nasional. Pengabaian terhadapnya justru membawa senjakala peradaban di kemudian hari. Segi humanisme yang dimaksudkan meliputi bagaimana subyek menemukan kedaulatan diri. Ki Hadjar memberi sinyal agar pendidikan berbasis kemanusiaan tak salah alamat, yakni memfokuskan pada prinsip penemuan bakat.
Jamak sekolah hari ini yang melupakan poin bakat sebagai titik krusial pembelajaran. Mereka cenderung mengikuti arus industri yang banyak mengeksplorasi keterampilan kerja. Hal ini bagus di satu sisi, namun di sisi lain perlu diimbangi dengan mengedepankan preferensi internal subyek. Bila tak demikian, peserta didik sebagai pihak pelaksana akan menjadi korban dari egoisme sekolah. [] bersambung
Peneliti Pendidikan, Penulis Buku Genealogi Hoaks Indonesia



Leave a Reply