belajar sama-sama
berkarya sama-sama
bekerja sama, sama***
semua orang, itu guru
alam raya, sekolahku
sejahtera bangsaku.
Merawat keragaman itu, meminjam Bahasa Pramudya Ananta Toer, semestinya sejak dalam pikiran, apalagi perbuatan. Dengan demikian, setiap ungkapan penghargaan atas ketidakseragaman tak boleh berhenti pada kata-kata atau terjebak pada jargon-jargon yang ujung-ujungnya adalah iklan komersial. Banyak fakta ditemukan, perihal mendidik dengan pendekatan multikulturalisme tetapi ternyata tak mampu dan tak sanggup menghadapi ujian ketidakseragaman dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, mencari cara agar anak maju seperti anak lain yang berprestasi dan juara dalam olimpiade atau kompetisi.

Makna tersebut telah dinarasikan dengan sangat apik oleh penulis prolog dan epilog dalam buku Kami Tidak Seragam. Dua tulisan pembuka Pandora ini sangat penting dibaca sebelum memasuki labirin pengetahuan di dalam buku ini. Saya kira, dua tulisan ini betul-betul menunjukkan saya jalan yang benar ,jalan yang penuh harapan dan suka cita, dan sesekali, juga akan berakhir pada ketidakmenentuan (njuk piye, njuk ngopo, njuk sopo, yo emboh…). Lalu, dokumentasi pengetahuan berikutnya menjadi niscaya untuk melanjutkan proses pembelajaran. Demikian seterusnya….tak pernah selesai.
Buku “Kami Tidak Seragam” itu seiring dan sejalan dengan kalimat “Kami Beragam”. Kalimat kedua sebetulnya tidak mengancam bagi siapa pun, namun kalimat pertama itu artinya ada upaya pembelaan terhadap kepentingan terbaik anak: seringkali dalam beragam praktik pendidikan, anak diperlakukan sama untuk minat yang tak sama, diukur dengan ukuran yang sama dalam minat belajarnya, dan diberikan hukuman sedemikian ‘menyakitkan’bagi yang kapasitas koginitifnya terlalu ketinggalan tanpa ada ganti ‘variabel’ lain apa yang dijadikan bahan apresiasi. Anak-anak yang sejatinya tidak seragam, memang, harus dibanding-bandingkan, yang tentu saja itu tindakan orang dewasa yang sangatlah konyol di mata anak-anak.
Anak-anak tahu kekonyolan itu, tapi merekalah manusia-manusia yang terlampau sabar menunggu. Menunggu orang dewasa (fasilitator, pendidik, guru, dll) mendapatkan ‘hidayah’ bahwa orang tua bukanlah penentu masa depan hidup anak-anaknya. Anak-anak tahu kekonyolan itu, tetapi, mereka sangat tahu bagaimana cara menertawakannya dan melaluinya.
Hidup itu bukan perlombaan?
Dari buku “Kami Tidak Seragam” yang lumayan mahal ini, saya mendapati banyak makna dari tiap-tiap goresan di dalamnya. Anak-anak yang bebas belajar itu, fasilitator yang sabar itu, dan lingkungan belajar yang ‘liar’ telah dengan sangat baik mendokumentasikan pengetahuan yang berangkat dari anak-anak, bukan dari pesanan otak orang dewasa apalagi pabrik-pabrik piagam penghargaan. Toh, mereka sangat bangga dengan apa yang dicapainya. Orang-orang tua, sebagian besar, saya kira turut bangga dengan dibukukannya karya anak-anak salam ini dengan sangat bagus. Kesadaran disertai kemampuan mendokumentasikan pengetahuan secara tertulis, visual, audio-visual, adalah capaian manusia paling berharga di semua peradaban manusia. Tanpa kemampuan itu, manusia hanyalah mewariskan abad kegelapan bagi generasi berikutnya. Sebaliknya, dengan dokumentasi pengetahuan yang dahsyat pula, peradaban bergerak maju dan membawa kemaslahatan untuk kehidupan sesama. Barangkali ini makna pertama yang penulis maksudkan.

Kedua, buku ini memberitahu secara halus bahwa sejatinya hidup dan belajar itu bukanlah upacara perlombaan yang berisikan menang dan kalah. Padahal menang hanyalah jadi arang, kalah juga menjadi abu. Itu tak pernah memberi manfaat jangka panjang. Ini kontek pendidikan anak-anak. Ini dalam konteks pendidikan kritis. Misalnya, Ki hajar memberikan tiga pijakan penting dalam proses belajar yaitu bahwasannya belajar itu dimaksudkan untuk hamemayu hayuning sariro, hamemayu hayuning bangsa, dan hamemayu hayuning bawono. Intinya belajar untuk memajukan diri, memajukan bangsa, dan menjaga alam raya.
Di buku ini jelas mengilustrasikan, anak-anak berkarya (riset) suka-suka: mulai tema dan tekhniknya, lalu memproses dengan riang gembira, walau kadang orang tuanya yang rada mumet. Tapi orang tua mumet itu kan soal biasa. Pada akhirnya semua bergembira….selamat juga untuk anak-anak yang berhasil membuat refleksi atas kegiatan riset merdeka tersebut. Nyaris, tak ada nuansa kalah-menang yang terbersit dari hati anak-anak atau di kepala para peneliti cilik ini. Semua berjalan, seperti alam terkembang menjadi guru.
Lalu bagaimana?
Eksperiment kelas riset merdeka sudah berakhir dengan indah dan gembira. Suatu ujicoba yang tak biasa walau dilakukan oleh sekolah yang biasa-biasa saja (Salam). Apa yang mau dipertanyakan? Buku ini telah menjadi bukti tak terbantahkan bahwa anak-anak yang dimerdekakan itu mampu belajar jauh melampaui pikiran-pikiran kita (orang tua, pendidik, penyelenggara pendidikan, fasilitator). Jadi, sebagaimana kata Amartya Sen, bahwa kemerdekaan dan kebebasan itu menjadi kunci utama pembangunan kesejahteraan suatu bangsa. Syarat ini absolut, katanya. Tak bisa ditawar-tawar apalagi minta diskon istimewa.
Saya tidak tahu persis bagaimana fasilitator belajar pendekatan Apreciative Inquiry (AI) yang dipelopori oleh Diana Whitney (2010) David Cooperider (2008)dalam praktik kerja sosial di Eropa dan menjalar ke beberapa negara lain di dunia. Brazil salah satu contoh yang berhasil.
Appreciative Inquiry merupakan salah satu metodologi dalam riset yang menggunakan pendekatan ‘kekuatan’ (strenght) atau aset (asset) untuk mencari pemecahan masalah. Atau biasa disebut sebagai pendekatan perubahan positif (positive approach to change). Sebenarnya, akar dari pendekatan ini adalah dengan melihat bukti‐bukti bahwa tendensi manusia, secara naluriah, adalah ‘curiga’, ‘berprasangka’ atas suatu hal yang tidak disukainya, suatu hal yang baru, atau suatu hal yang asing atau ingin diketahuinya.

Menurut Cooperrider dan Pratt (1995) setidaknya ada 4 prinisp panduan antara lain, pertama, penyelidikan dalam kehidupan organisasi/komunitas harus dimulai dengan penghargaan terhadap upaya dan pengalaman pelaku (appreciative). Dengan kata lain, kita harus belajar untuk mengerti apa yang kita miliki dan apa yang tidak ada/tersedia.
Kedua, penyelidikan untuk kemungkinan harus dapat direalisasikan demi tujuan yang hendak kita raih. Ketiga, penyelidikan yang “provokatif” sehingga proses tersebut harus membangkitkan kita dan menjadikankan kita mau bekerja untuk menyempurnakan hasil; dan keempat, penyelidikan harus bersifat kolaboratif. Dituntut pula situasi antar pelaku/subyek untuk saling mengerti satu sama lain untuk menciptakan perubahan secara sistematik.
Sementara tendensi lingkungan (orang tua dll) dapat bereaksi negatif atau mempertanyakan. Misalnya? Kelas riset mandiri ini membingungkan, bikin galau dan pusing orang tua. Tendensi ini wajar sekali. Tendensi atau reaksi negatif ini tentu berhubungan dengan kepentingan dari individu yang bersangkutan. Tak cuma individu, sebuah organisasi atau komunitas ‘wajar’ ketika ‘bereaksi negatif terhadap suatu hal yang belum dikenalinya. Mungkin kelumrahan seperti ini sering (dalam bahasa lebih positif atau lebih tepatnya meminjam istilah biologi ) disebut sebagai ‘kewaspadaan’. Fasilitator kelas riset di Salam rupanya secara sempurna memberdayakan kekuatan anak-anak dan alam raya untuk mendokumentasikan pengetahuan yang terserak, yang melimpah di sekeliling kita semua. Jadi, rupanya semua akan baik-baik saja.
Menurut saya AI ini tanpa disadari telah diterapkan di SALAM dalam konteks daur belajar dan praktik pendampingan oleh fasilitator. Tak ada salahnya kita sedikit mengintip pola kerja riset ala AI ini. Secara konseptual AI sudah cukup bagus untuk memperlihatkan kemampuan bekerja dengan membuat siklus kerja yang dinamakan 4D. Bagaimana AI bekerja dalam konsepnya bisa dilihat sebagai berikut:

Singkat ceritanya adalah bahwa AI melewati beberapa tahapan antara lain. Pertama adalah tahapan Cerita (Discovery). Proses awal adalah ‘mencari’ dengan menceritakan hal‐hal yang terbaik dalam hidup, berlanjut dalam bekerja dan bermasyarakat. Apa yang paling berkesan dalam hidup yang menyebabkan hidup (: bekerja) menjadi bermakna.
Kedua, adalah mimpi (Dream) yaitu Apa yang diinginkan dalam hidup (: bekerja), sehingga meningkatkan kualitas kehidupan, meningkatkan harapan pada masa depan. Ketiga, adalah Ubah (Design). Apa yang bisa diubah, nilai‐nilai apa yang mesti berubah agar proses mencapai perubahan dapat melanjutkan apa yang sudah dicapai sebelumnya. Apa mimpi kita tentang hal tersebut (bisa terkait dengan struktur, proses, dan prosedur)
Kempat, adalah kondisi (Destiny). Apa yang mesti dilakukan, bagaimana melakukannya (bisa terkait dengan struktur, proses, dan prosedur, tekhnologi). Ini yang disebut sebagai kekuatan arsitek sosial sebuah organisasi.
Proses AI dengan menggunakan pendekatan rentang waktu yang panjang dapat menjembatani masa lalu dengan masa kini atau menjembatani apa yang seharusnya dan apa yang sudah ada. Dan mengurangi resistensi yang disebabkan oleh kegagalan masa lalu (perasaan gagal, tanpa daya), karena berusaha mencari ‘nilai’ apa yang positif dari suatu peristiwa atau pengalaman, tanpa bersikap ahistoris dalam mendesain perubahan yang diinginkan, terutama perubahan ‘nilai’ dalam mencari kebaruan dan perubahan nilai dalam menjalani perubahan (transisi). Dalam tahap kondisi yang terjadi sebenarnya adalah ‘on going process’ yang terus menerus mesti diapresiasi secara positif.
Cerita ini harus berlanjut…!
Dari 24 dokumentasi hasil riset yang dibukukan sebagai jejak penelitian anak salam sangat tergambar bahwa anak-anak salam adalah anak yang beragam minatnya mulai dari ethnografi (diary, sejarah memancing, penjaga lingkungan, dll); biologi (binahong, ); tekhnologi mutakhir dengan robot-robot dan penelitian mesin; musik (gitar, ukulele), olahraga, seni fotografi, dan barangkali masih banyak lagi jika diexslplore dari disiplin ilmu. Tapi rasanya salam adalah pendidikan berbasis pengalaman sehari-hari jadi tidak perlu dibatasi dengan klaster ilmu. Lagian, proses pencariannya adalah proses-proses yang tak hampa atau kedap dari ruang sosial. Jadi, semuanya membelajarkan untuk menjadi manusia pembelajar yang harus menghargai sesama dan lingkungannya.

Pengarusutamaan “kami tidak seragam” barangkali merupakan agenda mendesak bangsa. Bangsa ini memang belum kelar dari zaman kegelapan, masyarakat yang gampang marah, susah menghargai, sulit menerima keragaman, dan negeri ini nyaris jadi negeri caci maki. Barangkali, dengan praktik peendidikan ‘Kami Tidak Seragam” ini dapat memberikan harapan baru kelak di hari-hari yang akan datang, agar bangsa ini, tak hancur lebur sebelum berkembang. Kesadaran akan keragaman potensi sejak usia dini, didukung lembaga pendidikan dan orang tua yang berkesadaran kritis, haruslah mampu menyumbang solusi atas kegalauan bangsa ini dari berbagai ancaman akhir-akhir ini. Kalau bukan anak-anak merdeka, pendidikan yang membebaskan, orang tua dan pendidik yang manusiawi, entah kepada siapa bangsa ini berharap dibenahi.
Foto-foto by: Yanuar Surya (Orang Tua SALAM)
Orang tua sekaligus murid SALAM. Penggiat Rumah Baca Komunitas (gerakan literasi). Penggiat Urban Literacy Campaign untuk komunitas.

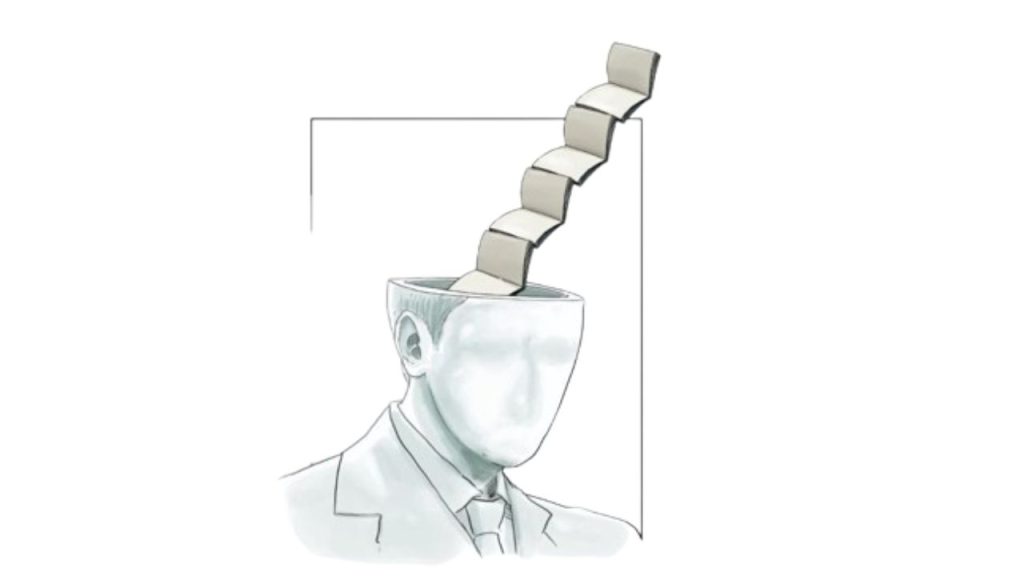

Leave a Reply