Subuh itu sesungguhnya saya masih mengantuk. Tapi, di mobil travel Pak Sopir berceloteh bagai siaran radio acara sapa pagi. Anak zaman sekarang masih usia SD sudah naik motor ke sekolah, ia mengawali dengan menggerutu. Dulu, pada tahun 60-an, anak-anak yang beruntung mendapat pendidikan Sekolah Rakyat, berangkat ke sekolah dengan berjalan belasan kilo, telanjang kaki pula. Sandal jepit merek S adalah identitas bocah yang punya kakek Mbah Lurah atau Mbah Camat. Kalau ada yang bersepatu, pasti ia anak Bupati. Ssst…Mbah Lurah zaman itu, konon istrinya sejumlah tiga bahkan enam!

Situasi sosial selalu dinamis. Unsur-unsur dalam ekosistem beradaptasi menemukan lingkungan yang aman dan nyaman untuk hidup. Demokrasi sudah makin baik. Jabatan-jabatan yang dahulu sakral hingga punya potensi otoriter dan anti-kritik kini makin egaliter. Celakanya, penghormatan yang makin setara ini membuat kerja banyak pejabat struktural maupun fungsional jadi makin apa adanya. Ada berita puluhan anggota dewan di Kota Malang tertangkap KPK. Juga para eks-koruptor, eks-tersangka pelecehan seksual, dan eks-habitus buruk sekaligus kriminal yang direstui UU untuk jadi calon wakil rakyat. Di masa lalu, banyak dongeng soal raja yang begitu dihormati bahkan disebut “khalifatullah” sebab betul-betul serius mengurusi rakyat. Jadi, mana yang lebih baik? Entahlah.
Syukurnya, kesadaran perempuan juga makin baik. Mbah Lurah zaman ini tidak lagi beristri tiga apalagi enam. Definisi keadilan, status sosial, kemandirian terus berubah seiring diseminasi ilmu pengetahuan yang semakin terbuka. Musuh keterbukaan ini adalah pihak-pihak dengan kekuasaan yang berusaha menutupi akses kepada sumber-sumber pengetahuan. Orde Soeharto memberikan pengalaman jenis ini, ketika kehormatan, moral, dan aktivitas apa yang baik serta buruk bagi perempuan didefinisikan negara lewat berbagai kebijakan dan alat-alatnya.

Tahun-tahun pasca-revolusi fisik, para guru harus mendatangi satu per satu pintu rumah buat mencari murid. Itu pun peruntungannya tipis. Masih mending kalau dijamu di rumah si empunya rumah, biasanya kalau tak diusir, ya dimaki-maki orangtua yang ketakutan pada bangku sekolahan. Hari ini, bocah baru bisa berjalan beberapa hari saja maunya langsung bisa baca tulis dan menguasai beragam keterampilan. Kalau bisa, sekalian yang level internasional. Soal biaya, wah, mendebarkan!
Pak Sopir meneruskan pengembaraan masa lalunya. Kali ini ia terperosok ke latar perkampungan di masa kanak-kanak. Bocah dulu menyikat gigi cukup pakai batu bata yang dihaluskan. Kalau ada yang sakit demam, cukup dibalur pakai irisan bawang merah dan minyak kelapa. Obat penyakit asma agak ekstrem, yakni kelelawar yang dibakar kering. Setelah menyebut soal khasiat alam itu, ia tergelak, “Sekarang, dikit-dikit mesti ke dokter, lalu dibekali obat berbungkus-bungkus ya!”
Lanjut, ia memprotes ibu hamil. Zaman dulu tak banyak bidan di kampung. Paling ada satu tenaga kesehatan di pusat kota. Aktivitas melahirkan tidak seprosedural hari ini, katanya. Sekarang baru berapa hari, harus konsultasi. Selang berapa minggu, konsultasi lagi. Pokoknya, sedikit demi sedikit konsultasi. Khusus soal ini saya sedikit protes, meski dalam batin. Soal ibu zaman dulu lancar melahirkan itu bisa jadi asumsi saja. Berbagai fasilitas kesehatan masa kini tentu sangat baik dalam mendukung kesehatan dan keselamatan ibu melahirkan dan anak.
Ngomong-ngomong soal pendidikan, celotehannya yang meluncur begitu saja tanpa perlu kalkulasi angka dan data itu benar belaka. Sekolah masa kini tak lagi mencetak tangan yang mengenali tanah, dedaunan, hewan, buah-buahan, dan unsur alam di sekitar kita sendiri. Jika ada kuis penyebutan nama-nama tanaman di sekitar, mungkin jawaban benar kita hanya beberapa saja. Sekolah farmasi mengenalkan pengetahuan yang kompatibel untuk industri farmasi. Begitu juga sekolah-sekolah dengan spesialisasi lainnya. Anak-anak dididik sebagai calon karyawan bergaji besar untuk sebuah industri mentereng, tapi minim kreativitas, daya cipta, dan keberanian untuk mengubah sektor-sektor yang nampak mapan.
Toto Rahardjo menulis buku berjudul Sekolah Biasa Saja. Buku itu tidak akan lahir jika Pak Toto tidak menyelenggarakan komunitas belajar Sanggar Anak Alam bersama istrinya, Bu Wahya di Kampung Nitiprayan, Bantul, Yogyakarta. Ia menggugat makna sekolah, yang awal mula dalam sejarah manusia muncul sebagai aktivitas belajar di waktu luang menjadi aktivitas yang serba wajib dan bersifat seragam, bahkan berubah memperalat manusia dalam struktur kebudayaan yang serba silang sengkarut ini.

Sanggar Anak Alam belajar segala sesuatu ketika anak menyadari kebutuhan untuk mempelajari hal itu. Ketika belajar berhitung, anak-anak menyadari fungsi dari menghitung, pada ekosistem apa saja hitungan itu digunakan, serta apa filosofi hitungan untuk menggerakkan fenomena politik, ekonomi, dan sosial budaya di sekitar mereka. Semua fenomena itu disebut dengan peristiwa kebudayaan.
Mereka menyebut para pengajar dengan sebutan fasilitator yang kebanyakan juga adalah orangtua anak-anak. Tidak ada satu orang pun dalam komunitas belajar yang merupakan sumber pengetahuan terpusat, melainkan semua kepala saling belajar dan saling mendengar satu sama lain. Tiap-tiap kepala menyimpan rasa ingin tahu, sebagaimana tiap-tiap kepala bertanggung jawab memecahkan rasa ingin tahu mereka, lalu membuat penemuannya jadi relevan dengan unsur budaya di sekitarnya.
Sepertinya siklus belajar semacam itu mirip dengan Imam Malik yang menasihati Khalifah Harun Al Rasyid ketika memintanya datang ke istana untuk berceramah, “Al ‘ilm yu’ta wa la ya’ti.” Kata Imam Malik, ilmu itu didatangi, bukan sebaliknya.
Teloleeet, teloleeet. Iring-iringan mobil polisi bersirine sahut-menyahut. O iya, ternyata kita masih bersama Pak Sopir. Pak Sopir mengambil posisi menepi. Ternyata, biang kehebohan adalah mobil plat merah berjumlah satu saja.
“Orang hebat begitu ya. Pengawalnya banyak,” penumpang lain menyahut.
“Apanya yang hebat? Ke mana pergi dikawal begitu. Coba tengok sopir truk yang pergi ke mana saja sendirian, temannya cuma barang muatan di bak belakang. Itu baru hebat!” Lalu, semua penumpang terbahak-bahak.
Menyenangkan sekali berjumpa seorang sopir anti-cemas yang menghayati hidup dari balik setir di jalan raya sebenar-benarnya, bukan dari jalan raya linimasa sosial media yang penuh berita menakutkan. Si sopir pasti menganut mazhab kebijaksanaan ala Confusius: Saya Dengar, Saya Lupa. Saya Lihat, Saya Ingat. Saya Lakukan, Saya Paham. Saya Temukan, Saya Kuasai.
Ah, ya. Ia sangat menguasai semua penumpang dan menjadi pusat perhatian sepanjang pagi.
menulis opini dan penerjemah. Aktif sebagai periset dan tim media kreatif Jaringan Nasional Gusdurian


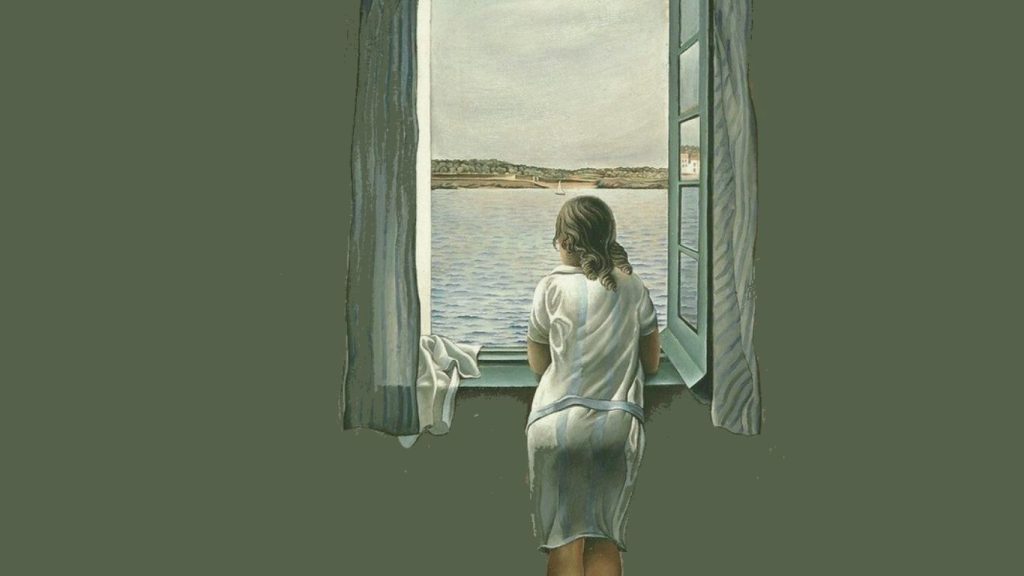
Leave a Reply